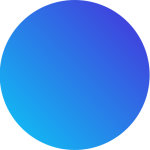ASPEK HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT[1]
Oleh : Jantje Tjiptabudy[2]
A. Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km2 dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (environmental service) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 : 5).
Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem tersebut meliputi terumbu karang, padang laut (sea grass), rumput laut (sea weeds) dan hutan bakau (mangrove). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kirna raksasa (tridacns gigas) dan teripang.
Selama ini kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian yang berarti karena pembangunan nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Selain itu aspek hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang mendiami kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil padahal selama ini mereka dengan hak ulayat laut-nya melakukan penguasaan dan pengelolaan atas kawasan tersebut.
Semua provinsi di Indonesia mempunyai wilayah pesisir, sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan juga mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek pasisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 2 ayat 3 butir 2d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000).
Berdasarkan realitas dan pengalaman yang terjadi ternyata implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, sering berbenturan dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat dan juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil
Masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Jika dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung turun temurun dan dihormati, belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha.
Khusus menyangkut hak-hak adat atas pesisir dan lautan, Titahelu (2000: 164) mengemukakan bahwa ada beberapa unsur yang menandai adanya wilayah petuanan laut dari masyarakat adat pesisir yaitu :
(1) Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya.
(2) Adanya kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut
(3) Dilakukan secara turun-temurun.
(4) Dilakukan secara periodik.
(5) Senantiasa dipertahankan terhadap pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat adat tersebut.
Penguasaan riil atas wilayah oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut dan umumnya adalah sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Di dalam wilayah ini sebenarnya secara de yure terdapat wewenang dari komunitas masyarakat adat. Wewenang yang dimaksudkan disini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam menurut prinsip-prinsip hukum adat dengan kekhasan masing-masing.
Ketika pengelolaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dikelola oleh kelompok pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah maka hak-hak masyarakat adat menjadi tersingkir. Jadi dalam kenyataan penguasaan dan pengaturan atas wilayah perairan pesisir dan pulau-puau kecil yang potensial senantiasa menjadi kepentingan pengusaha dan didukung oleh pemerintah sehingga kepentingan dari masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat adat terabaikan.
Berkaitan dengan batas-batas dan wewenang yang dimiliki -dengan komunitas masyarakat adat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah menentukan batas kewenangan di laut bagi kabupaten dan kota sejauh 4 mil laut, dan 4 mil sampai 12 mil bagi provinsi. Hal ini mengandung dua pengertian yakni : (1) adanya pengabaian dari negara; (2) hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang ada tidak diatur oleh negara, namun negara memandang hukum adat tersebut dapat digeser melalui berbagai kebijakan dalam kurun waktu tertentu.
Keadaan yang demikian pasti menimbulkan ketidak seimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan ( ulayat ) baik di laut maupun di darat. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan dalam penguasaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat adat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang batas wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam perspektif ini terdapat juga sebuah pengakuan yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara yang dapat dikategorikan sebagai pengakuan obyektif.
Penerapan keseimbangan disini pada hekikatnya adalah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan negara maupun kepentingan swasta pada satu sisi dan pada sisi yang lain perlu diperhatikan kepentingan masyarakat adat juga. Dengan demikian wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diimplementasikan dengan baik, berdasarkan nilai, asas dan norma dalam suatu nuansa yang harmonis tanpa menimbulkan konflik. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang diidengtifikasikan untuk mendapat solusi penyelesaian adalah sebagai berikut, bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap eksistensi masyarakat adat.
B. Pembahasan
1. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil.
1.1. Kebijakan Pemerintah
Indonesia sebagai Negara hukum, termasuk kategori Negara hukum modern. Konsepsi Negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan Negara yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Nomrmalisasi tujuan Negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial (Bagir Manan, 1995 : 55). Atas dasar itu pula, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Keterkaitan hak penguasaan Negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Bagir Manan (dalam Abrar Saleng, 2004: 17) akan mewujudkan kewajiban Negara :
(1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
(2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;
(3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan bestuursdaad dan beheersdaad dan tidak melakukan eigensdaad. Artinya secara a contrario, apabila hak penguasaan Negara diartikan sebagai eigensdaad maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh Negara atau hak penguasaan Negara sebagai berikut:
(1) Penguasaan semacam pemilikan oleh Negara. Artinya Negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya. Termasuk di sini bumi, air dan kekayaaan yang terkandung di dalamnya.
(2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;
(3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.
Apabila konsep Negara kesejahteraan dan fungsi Negara menurut W. Friedmann dikaitkan dengan konsepsi hak penguasaan Negara untuk kondisi Indonesia dapat diterima dengan beberapa kajian kritis sebagai berikut (Abrar Saleng, 2004 : 18-19) :
Pertama, hak penguasaan Negara yang dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 memposisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi Negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumberdaya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus. Karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh Negara.
Kedua, hak penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD 1945, membenarkan Negara untuk mengusahakan sumberdaya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public service atas dasar pertimbangan : filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoly yang merugikan perekonomian Negara), ekonomi (efisien dan efektifitas) dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Khusus berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya laut maka dapat dijelaskan bahwa paling sedikit terdapat tiga ciri dari kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang dipraktekkan selama ini, yakni (1) sentralistik, (2) didasarkan pada dokrin common property dan (3) mengabaikan pluralism hukum.
Sentralistik kebijakan menyangkut substansi sekaligus proses pembuatannya. Substansi kebijakan yang sentralistik tercermin pada kewenangan pengelolaan sumberdaya laut, setidak-tidaknya hak itu terjadi disektor perikanan. Disektor ini, proses perizinan maupun pejabat yang berwenang memberikan hampir seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kalaupun ada pendelegasian kewenangan kepada gubernur, hal itu semata-mata dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
Demikian pula proses penetapan kebijakannya, hampir semuanya melibatkan pemerintah pusat. Indikasinya, kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut pada umumnya dikemas dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden yang dalam proses penetapannya semata-mata melibatkan aparat pemerintah pusat.
Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang diasarkan pada common property sebagai ciri kedua juga mengandung sejumlah kelemahan. Dengan mendasarkan kebijakan pada dokrin common property maka laut diposisikan sebagai sumberdaya milik bersama. Konsekuensinya, laut diperlakukan laksana harta tak betuan dimana setiap orang leluasa melakkukan okupasi dan eksploitasi (open access). Karakteristik seperti ini sangat jelas dalam Undang-Undang Perikanan dan kebijakan lainnya. Ini pula yang antara lain melatar belakangi munculnya berbagai konflik dalam penggunaan sumberdaya terutama antara nelayan tradisonal dengan perusahaan penangkapan ikan.
Sebagai dasar pembentukan kebijakan pengelolaan laut, dokrin common property sesungguhnya mempunyai banyak kelemahan. Francois T Christy (dalam M. Arif Nasution dkk, 2005 : 105) mengungkapkan adanya empat akibat buruk dari suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang didasarkan pada dokrin common property yaitu (a) pemborosan sumberdaya secara fisik, (b) inefisiensi secara ekonomi, (3) kemiskinan nelayan, dan (4) konflik antara pengguna sumberdaya.
Sementara pengabaian pluralism hukum, yang merupakan ciri ketiga dari kebijakan pengelolaan laut selama ini, menjelama dalam bentuk ketiadaan pengakuan terhadap sistem pengeloaan sumberdaya laut berdasarkan hukum adat. Padahal secara faktual sistem pengelolaan semacam itu masih dipraktekkan di berbagai daerah. Beberap contoh yang dapat dikemukakan, seperti sistem hak wilayah laut di Maluku atau perikanan Bagang dan romping di Sulawesi Selatan. Bahkan pada derajat tertentu, pluralism hukum dalam pengelolaan sumberdaya laut juga mengisyaratkan bahwa laut dapat menjadi obyek pemilikan tunggal, sesuatuyang berbeda secara diametal dengan doktrin common property.
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
Undang-undang ini menentukan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah (a) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, hak dan kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Di dalam UUPA diatur mengenai hak menguasai oleh Negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga diatur hak ulayat, hak-hak atas tanah, dan hak atas air.
(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tersebut lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumberdaya alam. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang-Undang ini terkesan lebih menitik beratkan perhatian pada eksploitasi dari pada kelestarian sumberdaya tambang. Di dalam undang-undang ini hanya terdapat satu pasal perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan.
(5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang
Pembentukan Undang-undang Tata Ruang didasarkan pada asas-asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan asas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Undang-undang Tata Ruang mengatur tata ruang yang meliputi darat, laut dan udara, sehingga undang-undang ini sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud di atas memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
(a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
(b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
(c) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai hutan.
Penguasaan hutan Negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
(7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya alam beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”
Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan masih berjalan pada semangat sentralistik. Ruang bagi partisipasi public dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan ikan tidak ditemukan dalam undang-undang Perikanan. Demikian pula perlindungan pada hak masyarakat adat. Tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang ini yang menyebutkan tentang masyarakat adat dan hak-haknya atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya ikan.
(8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan.
Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang perairan, pengaturan air dibatasi pada air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah, dan tidak termasuk ait yang terdapat di laut.
(9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Di dalam undang-undang ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola perairan laut pesisir dan perairan laut pulau-pulau kecil sampai batas 12 mil.
(10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan.
Undang-undang Hankam ini mengatur mengenai pengamanan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang dilaksanakan dengan konservasi dan diversifikasi serta didayagunakan bagi kepentingan pertanahan keamanan Negara.
(11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawitasataan.
Di dalam Undang-undang Keparawisataan diatur pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.
1.2. Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Haknya.
Menurut Soekanto (1983 : 3), masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum, oleh karena bersifat otonom, yang kemudian disebut otonomi desa; artinya masyarakat hukum tersebut menyelenggarakan perbuatan hukum, misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat , menyelenggarakan peradilan, mengatur penggunaan tanah, mewarisi dan sebagainya.
Menurut Ter Haar (Riyanto , 2004 : 7), masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
Soepomo (Riyanto, 2004 : 7-8) dalam mendiskripsikan masyarakat hukun adat/persekutuan hukum adat menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, menurut dasar susunannya, yaitu (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis); dan (b) yang mendasarkan lingkungan daerah (territorial).
Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki berbagai kepentingan yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, hukum, politik, perekonomian, sejarah dan hak atas kehidupan otonom. Masyarakat adat juga memiliki lingkungan alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kebebasan untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya alam secara arif (Titahelu : 1998)
Salah satu antropolog Indonesia yaitu Koentjaraningrat (1993) menggunakan istilah masyarakat terasing yaitu masyarakat yang terisolasi dan memiliki kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain yang lebih maju. Kelompok masyarakat tersebut bersifat terbelakang serta tertinggal dalam prsoses mengembangkan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan ideologi.
Soebroto (1999) menggunakan istilah masyarakat adat untuk menunjukkan kelompok masyarakat itu dengan karakteristik bersifat otonom yaitu kuasa untuk mengatur sistem kehidupannya sendiri (hukum, politik, ekonomi) dan bersifat otonom yaitu suatu kesatuan yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.
Hasil dari kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara merumuskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Rudito, 1999).
Hubungan-hubungan sosial antar anggota persekutuan masyarakat adat diatur oleh hukum adat yang mengatur hubungan-hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumber-sumber alam diwilayah mereka.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dari hukum adat akan muncul konsepsi tentang hak adat. Pada dasarnya hak adat dapat dikatakan sebagai hak masyarakat adat untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya. Dalam konsep hak tenurial adat, subyek hukum yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber alam hanyalah anggota masyarakat adat setempat, yang bukan anggota masyarakat adat setempat tidak memiliki hak apapun, kecuali atas izin masyarakat adat yang bersangkutan, sebab inti dari hak adat adalah kedaulatan masyarakat adat setempat atas wilayah mereka.
Identifikasi tentang masyarakat adat bukan saja berkaitan pada konsep-konsep yuridis tentang apa yang disebut sebagai masyarakat adat dan dimanakah kedudukannya, tetapi pada dasarnya juga mengarah pada suatu tuntutan pengakuan dari masyarakat adat atas hak-hak mereka yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai masyarakat adat. Tuntutan pengakuan dari masyarakat adat atas hak-hak mereka berpegang pada dua hal yaitu :
· Kedudukannya sebagai komunitas masyarakat adat;
· Berakar pada susunan asli dan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
Pengakuan atas eksistensi atau keberadaan masyarakat adat sangat beragam satu dengan lainnya. Demikian pula bentuk pengakuan terhadap eksistensi atau keberadaan masyarakat adat oleh pemerintah daerah yang berbeda. Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi ke dalam kebijakan-kebijakan perundang-undangan Republik Indonesia dan juga wacana-wacana masyarakat di tingkat nasional misalnya antara lain tentang sistem penguasaan tanah.
Hukum adat sebenarnya mengakui bahwa penguasaan suatu wilayah petuanan negeri ditandai dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari warga atau anak negeri tersebut, misalnya dengan kegiatan berkebun, berburu untuk mencari hasil hutan dan sebagainya ( Ter Haar ) Semua ini merupakan bukti bahwa warga atau anak negeri dari negeri tersebut telah berulang kali mengusahakan tempat atau wilayah tersebut, sehingga secara nyata (de facto) mereka menguasai wilayah tersebut. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah secara hukum (de yure) hal itu dapat diterima. Berkaitan dengan masalah hukum ini sebenarnya harus dibarengi atau diikuti dengan pengakuan baik lisan maupun tertulis bahwa wilayah tersebut memang milik warga atau milik negeri tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari kesepakatan-kesepakatan antar warga atau negeri-negeri tertentu, yang ditaati oleh mereka baik secara individu (pribadi) maupun warga masyarakat negeri secara keseluruhan.
Patut diakui bahwa penguasaan baik de facto maupun de yure seperti disebutkan di atas kadang-kadang tidak di akui juga oleh penguasa negara, sehingga melahirkan konflik atau pertentangan. Negara hadir dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang cenderung merugikan warganya sendiri. Padahal negara seharusnya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber-sumber (Sumber-sumber Agraria meliputi tanah atau bumi dan barang-barang atau benda-benda yang terkandung didalamnya termasuk dalam wilayah perairan maupun udara ) agraria yang mereka miliki.
Selama ini ada kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat adat ialah batas-batas wilayah yang kurang jelas, siapa pemegang hak atas wilayah tersebut, objek apa saja yang ada di atas tanah tersebut dan jenis hak apa saja yang melekat pada bidang tanah itu dan sebagainya. Kondisi inilah yang membuat masyarakat adat mempunyai kemampuan tawar-menawar (bargaining power) yang agak lemah, menghadapi pihak-pihak tertentu, katakanlah pemerintah dan pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan uang.
Masyarakat yang mengakui keberadaannya sebagai masyarakat adat, tidak dapat diterima begitu saja, tetapi harus memperlihatkan identitas, kriteria dan aktivitas tertentu yang mencerminkan nilai-nilai dan norma sebagai suatu masyarakat adat.
Pengelolaan atas sumberdaya laut pada hakikatnya berjalan beriringan dengan pengelolaan atas sumberdaya yang ada di darat. Jadi, sumber daya di darat maupun sumberdaya di laut adalah merupakan milik masyarakat adat. Dikatakan sebagai suatu milik dari masyarakat berarti adanya hak dari masyarakat itu diatas suatu wilayah tertentu yang cukup luas. Hak tersebut bukan merupakan hak yang disebut bersifat hukum privat ataupun bersifat hukum public, tetapi merupakan sekumpulan hak dan kewajiban dari (a) masyarakat atau keluarga anggota masyarakat adat; (b) masyarakat adat secara bersama-sama, dan (c) orang lain bukan anggota masyarakat adat tetapi memperoleh ijin memakai atau menggunakan tanah dengan memenuhi syaratr-syarat tertentu sebelumnya, yakni membayar sesuatu (recognitie).
Apa yang dikemukakan terakhir ini menunjukkan bahwa masyarakat adat yang menempati peisisr laut, memiliki wilayah petuanan atau wilayah ulayat yang dapat berada di darat maupun di pesisir laut.
Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan pada pulau-pulau kecil, maka hukum adat dan hukum kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang memukimi pesisir dan pulau-pulau kecil, merupakan salah satu akses yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber-sumber daya alam setempat, dan juga untuk melindungi sumberdaya tersebut terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi berupa degradasi, atau eksploitasi berlebihan. Negara seringkali tidak dapat melakukan pengawasan jauh sampai ke dalam lingkup dimana usaha-usaha berskala kecil, menengah maupun besar beroperasi di wilayah pesisir dan laut atau pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Sebaliknya, tempat-tempat usaha tersebut banyak berada disekitar bahkan ditengah-tengah masyarakat yang memukimi pesisir maupun pulau-pulau kecil.
2. Kewenangan dan Hak
2.1. Hak Menguasai Negara.
Konsep dasar hak menguasai oleh Negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut tampak bahwa menurut konsep UUD 1945, hubungan antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang dimaksud dengan “dikuasai” oleh Negara, dalam UUD 1945 tidak ada penjelasan.
Penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalmnya (disebut sumber daya alam) dikuasai Negara, termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 2 UUPA yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai sumberdaya alam oleh Negara sebagai berikut :
(1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
(2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
o Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
o Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
o Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakatr dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan Pasal 2 UUPA tersebut, maka menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur 3 hal yaitu :
o Mengatur dan menyelenggatakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan;
o Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
o Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh Negara tersebut semata-mata “bersifat public”, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai secara fisik dan dan menggunakan sebagaimana wewenang hak yang “bersifat pribadi” (Muhammad Bakri, 2007 : 5). Selanjutnya esensi istilah “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai konsekuensi dari kata-kata “dikuasai oleh Negara” dan “dipergunakan”. Meskipun kedua kata mempunyai arti yang berbeda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama dan saling berkaitan. Sebab “dipergunakan” merupakan tujuan dari kata “dikuasai”, sehingga keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata “dipergunakan” sebagai akibat adanya “penguasaan negara”. (H. Abrar Saleng, 2004 : 37).
Kedua aspek kaidah tersebut tidak dapat dipsahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematik, hak penguasaan Negara merupakan intrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (objectives).
Istilah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan kelanjutan atau normatifisasi dari beberapa istilah dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 seperti “… memajukan kesejahteraan umum, … perdamaian abadi dan keadilan sosial, … serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia….” Mengenai kata rakyat, selain berhubungan dengan kata kemakmuran dan keadilan sosial, juga berhubungan dengan faham kedaulatan dan lembaga perwakilan seperti : Dewan Perwakilan Rakyat. Selain hubungan-hubungan tersebut di atas, rakyat juga dapat dilahami dalam tiga kemungkinan (Jimly Asshiddiqie, 1994 : 63-64) :
(a) Rakyat sebagai individu atau bersifat individual (perorangan). Sebagai individu rakyat adalah otonom yang memiliki khak dan kewajiban yang dirinci dalam konstitusi suatu Negara.
(b) Rakyat sebagai golongan-golongan atau kelas. Rakyat dalam faham kedaulatan, bukanlah rakyat sebagai individu-individu melainkan rakyat sebagai keseluruhan yang meliputi berbagai golongan-golongan dalam masyarakat.
(c) Rakyat yang mengabaikan dikotomi baik berdasarkan individual maupun golongan-golongan.
Ketiga golongan hubungan tersebut, oleh Soepomo (dalam Muhammad Yamin, 1971 : 112-113) disebutkan sebagai teori yang mendasari aliran-aliran pikiran kenegaraan, yaitu aliran perorangan (individualisme), aliran teori golongan yang komunistik dan aliran teori integralistik yang bersifat totaliter.
Sejalan demgan pengertian-pengertian di atas, Philipus Hadjon (1987 : 1) menyebutkan cakupan pengertian rakyat : Pertama, menganfung hakikat subordinasi yang diperintyah sebagai lawan dari pemerintah; Kedua, secara limitative dan enunsiatif membedakan hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum. Pengertian rakyat di dalam UUD 1945 sebagai subjek mengandung makna subordonasi terhadap yang memerintah. Bahkan antara rakyat dan pemerintah merupakan suatu totalitas sebagaimana dikemukakan Soepomo dapat dimengerti secara politis tetapi tidak dalam pengertian yuridis.
Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warganegara.
2.2. Kewenangan Pemerintah Pusat
Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang disertai sistem desentralisasi susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi Negara tingkat pusat dan tingkat daerah.
Susunan organisasi negara tingkat pusat, mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintah dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulen) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.
Konsekuensi sistem desntralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan akan dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (medebewind).
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintah yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah yang bersangkutan.
Pemberian kewenangan kepada daerah dilandasi kepada asas desentralisasi, maka akan memberi implikasi berupa penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
Berkaitan dengan bidang kelautan kewenangan Pemerintah meliputi (Kuntoro, 2002 : 8) :
a. penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar laut serta ZEE dan landas kontinen.
b. Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pengeloaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritime yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
e. Penegakan hukum diwilayah laut diluar 12 mil dan didalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.
Keleluasan otonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Dalam pembangunan kawasan pesisir dan pantai suatu provinsi merupakan suatu sub sistem dalam pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pembangunan kawasan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dan sekaligus menyatu dengan pembangunan nasional, yang penyelenggaraannya mengacu kepada kaedah hukum penuntun, dan merupakan pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kawasan atau wilayah tersebut.
2.3. Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 maka pelimpahan kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, dinyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) s.d. ayat (4) :
(1) Daerah yang memilkiki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
(2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau didasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b. pengaturan administrasi;
c. pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan/atau kea rah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten kota.
Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah kearah kesejahteraan rakyat terhadap bverbagai potensi sumberdaya kelautan yang dimilikinya. Terutama bagi masyarakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir.
Perhatian Pemerintah maupun pemerintah daerah terhadap wilayah pesisir yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumberdaya atau akibat bencana alam pada satu sisi dan pada sisi yang lain yaitu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir serta dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir.
Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relative kurang. Selain itu kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, serta terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat teritama masyarakat (adat) pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan.
2.4. Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas Pesisir dan Laut
Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, sea tenure. Sudo (1983) yang mengutip Laundgaarde, mengatakan bahwa istilah sea tenure mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Sea tenure adalah suatu sistem, dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi terhadap wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan (over exploitation).
Melengkapi batasan Sudo, seorang ilmuan lain yaitu Akimichi Tomoya (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan (property rights) mempunyai konotasi sebagai memiliki (to own), memasuki (to access) dan memanfaatkan (to use). Baik konotasi memiliki, memasuki maupun memanfaatkan tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan (fishing ground), tetapi juga mengacu pada teknik-teknik penangkapan, peralatan yang digunakan (teknologi) atau bahkan sumberdaya yang ditangkap dan dikumpulkan.
Dengan demikian maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pada desa (negeri-negeri untuk Maluku Tengah).
Perangkat aturan atau hak adat kelautan (hak ulayat laut) ini menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperbolehkan yang ada dalam suatu wilayah laut.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hak ulayat laut mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam institusi pemilikan bersama. Istilah pemilikan bersama disini merujuk pada pembagian hak-hak penguasaan bersama di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tertentu. Konsep milik jika diterapkan pada sumberdaya mengandung arti sebagai suatu kelembagaan sosial primer yang memiliki susunan dan fungsi untuk mengatur sumberdaya yang lebih didasarkan pada kebiasaan, larangan-larangan dan kekeluargaan. Oleh karena itu institusi atau kepranataan dalam sistem kepemilikan atau penguasaan sumberdaya bersama tidak dapat dilepaskan dari adanya sosial order yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap individu anggota suatu komunitas.
Aturan-aturan yang terbentuk dalam sistem penguasaan bersama itu pada dasarnya merupakan suatu kesadaran kolektif (collective consciousness). Dalam hal ini kesadaran kolektif itu mempunyai dua sifat pokok (Wahyono dkk, 2000 : 8 – 9). Pertama, mengandung pengertian bahwa kesadaran kolektif dari suatu komunitas atau kelompok sosial sesungguhnya berada di luar ke-diri-an dari setiap individu anggota masyarakat. Jadi kesadaran kolektif itu tidak tergantung keberadaannya pada eksistensi dari setiap individu, melainkan sebaliknya, yaitu selalu diwariskan atau disosialisasikan dari suatu nenerasi ke generasi berikutnya. Sifat yang kedua, kesadaran kolektif mengandung suatu kekuatan psikis yang memaksa individu-individu anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadapnya.
Berdasarkan pada gambaran sebagaimana dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi hak ulayat laut dalam suatu komunitas dapat dilihat dari seberapa jauh institusi hak ulayat laut itu memberikan kestabilan struktur sosial suatu komunitas tersebut. Tentang hak ini Brown (Zerner, 1993 : 76)
“……define the sosial function of sosially standardized mode of activity or of thought, as its relation to the sosial structure to the existence and continuity of which it makes some contribution”
Melihat uraian diatas, pengertian fungsi pada hak ulayat laut adalah menunjuk pada suatu proses hubungan sosial yang dinamis dalam suatu sistem sosial atau struktur masyarakat tempat hak ulayat laut itu dipraktekkan. Berkaitan dengan ini Robert K Merton (Zerner, 1993 : 106) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis fungsional pada suatu kepranataan sosial sebaiknya lebih ditekankan pada permasalahan yang konkret, yaitu bagaimana mekanisme sosial sebuah lembaga kepranataan sosial itu berlangsung, seperti antara lain pembagian peran, penyekatan kelembagaan, susunan nilai-nilai, pembagian kerja dan praktek-praktek ritual.
Merton membedakan fungsi kedalam dua hal, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Menurut Merton sesuatu memiliki fungsi manifest apabila :
“…… those objective consequences contributing to the adjustment or adation of the sistem which are intended and recognized by participant in the sistem “(dalam Zerner, 1993 : 105).
Adapun fungsi laten berkaitan dengan : …. those which are neither nor recognized. Apabila dikaitkan dengan hak ulayat laut, maka fungsi manifest menunjuk pada pengertian berbagai konsekuensi praktek hak ulayat laut yang disadari oleh setiap anggota masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat atau integrasi sosial, sedangkan berbagai konsekuensi dari praktek hak ulayat laut yang tidak didasari merupakan fungsi laten dari hak ulayat laut tersebut.
Dalam kaitan ini, Johanes memberikan contoh fungsi-fungsi yang terdapat dalam hak ulayat laut sebagai berikut:
“Costumary marine tenurecan play a number of valuable roles and contempory fisheries management. It can : (1) provide cultural sanctioned rules for allocating marine resources acquitable, apprehending and punishing trangressord and adjudicating disputes (usually without resource to government, thereby greatly reducing administrative cost); (2) function as a from of conservation measure by limiting entry to a fishery and providing the owners with an incentive ti regukate their own harvest; and (3) facilitate more flexible adjustments to changing biological or socio economic conditions affecting the fishery than do government regulation”
Suatu bahasan mengenai hak ulayat laut dalam bentuk yang lebih dinamis lahir dari pertanyaan pokok, yaitu mengapa hak ulayat laut dipraktekkan oleh suatu masyarakat dan factor-faktor apa yang mempengaruhinya. Belum ada suatu teori yang mampu menjawab secara tuntas pertanyaan ini. Akan tetapi cukup banyak hipotetis yang berusaha menjawab pertanyaan ini dengan acuan kasus-kasus tertentu. Ini berarti ada banyak variabel yang mengarah ada atau tidaknya aturan dan praktek hak ulayat laut pada suatu masyarakat. Meskipun demikian, suatu hal yang merupakan kunci mengenai hal ini adalah anggapan bahwa laut merupakan suatu sumberdaya yang bernilai.
Banyak hal yang kemudian mengarah pada anggapan bahwa sumberdaya laut bernilai tinggi atau sebaliknya. Pertama, misalnya tingkat kepentingan laut. Kedua, laut juga bisa dikatakan bernilai jika memiliki sumberdaya, dan kondisi ekologisnya sedemikian rupa sehingga orang mudah mengeksploitasinya. Dalam hal yang terakhir ini, tentu berhubungan pula dengan mudah atau tidaknya proses distribusi berjalan, atau dengan kata lain ada atau tidaknya pasar. Kondisi pasar itu sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat lain, sehingga kemungkinan intensitas terjadinya proses tukar menukar semakin besar.
Satu variabel yang berbeda dengan variabel-variabel di atas adalah sistem kepercayaan. Pada sistem kepercayaan masyarakat tertentu, laut mungkin dianggap sebagai sumber kehidupannya. Dengan latar belakang kepercayaan ini, maka perlakuan masyarakat terhadap laut berbeda, termasuk masalah yang berhubungan dengan berkembang atau tidaknya hak penguasaan laut tersebut.
Selanjutnya, apabila variabel-variabel di atas diidentifikasikan dalam upaya mencari jawaban mengapa hak ulayat laut dipraktekkan oleh suatu masyarakat, maka jawaban atas variabel-variabel apa yang mempengaruhi berlangsungnya hak ulayat laut, lebih banyak terikat pada suatu variabel kunci yaitu konflik (Pollnac : 1984). Hal ini disebabkan oleh karena konflik merupakan suatu potensi yang cukup kuat atas berubahnya hak ulayat laut. Dalam hal ini perubahan-perubahan yang terjadi sangat bervariasi, dari mulai perubahan isi aturan maupun praktek hak ulayat laut sampai pada perubahan yang menyangkut semakin menguat atau melemahnya praktek pelaksanaan aturan hak ulayat laut tersebut.
2.5. Hak Ulayat dan Hak Penguasaan Negara.
Hak ulayat tidak sama dengan hak penguasaan Negara yang bersumber dari konstitusi Negara. Hak ulayat yang diakui dan disebut dalam Pasal 3 UUPA. Pengakuan eksistensi hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat berserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya UUD 1945 yang memuat konsep hak penguasaan Negara. UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah beschikkingsrecht dalam kepustakaan hukum adat. Maria S.W. Sumardjono (dalam Abrar Saleng, 2004 : 51) mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar di antara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa recognisi.
Dengan demikian hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat (subjek hak) dan sumber daya alam serta wilayah tertentu (objek hak). Hak ulayat berisi wewenang-wewenang yang menyatakan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan sumber-sumber alam/wilayahnya adalah hubungan penguasaan, bukan hubungan pemilikan. Hubungan hukum itu disebut ulayatnya yang bersal dari bahasa Minang yang berarti “wilayahnya” (Boedi Harsono, 1975 : 83).
Berdasarkan pengertian dan pandangan teoritis di atas, maka terdapat indikasi adanya hubungan persamaan dan perbedaan antara hak ulayat dengan hak penguasaan Negara yaitu (Abrar Saleng, 2004 : 52) :
(a) Subjeknya, bagi hak ulayat adalah masyarakat hukum, bukan perorangan, sedangkan bagi hak menguasai Negara adalah Negara.
(b) Objeknya, bagi hak ulayat adalah tanah, air dan sumber-sumber alam (tertentu) dalam wilayahnya, sedangkan hak menguasai Negara lebih luas, sebab selain semua potensi sumberdaya alam yang ada dalam wilayah Negara Indonesia, juga cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
(c) Isinya, bagi hak ulayat adalah rangkaian wewenang dan kewajiban yang meliputi : pengaturan, pemberian cara penggunaan sumberdaya alam dan pemeliharaannya, sedangkan bagi hak menguasai Negara adalah sejumlah wewenang dan kewajiban public yang meliputi : pengaturan, pengutrusan serta pengawasan penggunaan dan pemanfaatan segenap potensi sumberdaya alam dan cabang-cabang produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(d) Pelaksana, bagi hak ulayat adalah Kepala Persekutuan Hukum atau kepala adat, sedangkan bagi hak penguasaan Negara adalah pemerintah Republik Indonesia.
Berdasarkan perbedaan di atas, maka hak ulayat dapat dipersamakan dengan hak bangsa dan wewenang kepala persekutuan hukum adat dipersamakan dengan hak penguasaan Negara. Ruang lingkup hak ulayat lebih sempit dan terbatas, sementara hak penguasaan Negara ruang lingkupnya nasional dan meliputi semua sumberdaya alam yang terdapat dalam tanah air Indonesia.
C. Eksistensi dan Keberlakuan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Hukum adat maupun hak faktual atau mungkin disebut juga sebagai hukum lokal, terhadap hal-hal tersebut yakni hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan pribadi, kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan alam lingkungan disekitarnya, pemilikan tanah adat, pesisir dan laut, hutan mangrove , jual beli hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan yang mengikuti hukum pasar. Khusus untuk pengelolaan pesisir dan perairan kepulauan, hukum adat maupun hukum faktual telah diakomodasi dalam peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten. Dijumpai bahwa banyak pulau yang sangat kecil sudah dihuni oleh penduduk sejak leluhurnya dan dipandang sebagai miliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika pemerintah seringkali pengeluarkan pendapat bahwa pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki oleh perorangan (Titahelu, 2003 : 4).
Dimaksudkan dengan hak faktual adalah hak yang berlaku dalam masyarakat lokal yang bukan berasal dari hukum adat. Hak ini adalah jenis hak yang tidak dapat diidentifikasi di dalam jenis-jenis hak yang dikenal dalam literatur hukum adat. Hak ini adalah hak yang batu timbul dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak masyarakat untuk menanam rumput laut di pesisir pulau tertentu. Menanam rumput laut tidak dikenal dalam hukum adat mereka. Hak ini adalah hak baru, begitu pula hak atas perairan disekitar rumpon, hak atas perairan disekitar keramba, hak atas perairan disekitar bagan. Antara masyarakat adat dengan pemerintah sering terjadi konflik, dan semakin dekat kepentingan berbagai pihak saling berhubungan, semakin tinggi konflik di atara para pihak. Sebaliknya semakin sedikit kepentingan saling berhubungan, semakin kecil konflik yang timbul. Konflik antara masyarakat berhadapan dengan investor asing atau domistik yang didukung pemerintah seperti kasus penangkapan ikan Napoleon di kawasan terumbu karang Metimarang dan Wekenau (sekitar pulau Luang Maluku Tenggara Barat). Konflik yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Konflik antara masyarakat adat Haruku dengan PT Aneka Tambang di wilayah petuanannya yang di sasi.
Apa yang dikemukakan di atas mencerminkan hubungan yang kuat dengan aspek sosiologis yang dikedepankan yakni adanya simbol atau lambang interaksi yang sistematis, terstruktur dan masih berlaku sampai saat ini. Hal ini menampakkan adanya norma atau kaedah tetap yang selain menjaga keteraturan atau ketertiban di lingkungan mereka sendiri, adalah juga digunakan unruk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Roberth Souhaly, 2006 : 74).
Peran hukum positif yang akan dibicarakan masih dalam lingkungan preskripsi yang ada di dalam sistem hukum. Artinya peran itu adalah menempatkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaedah yang member peluang, yang melandasi dua hal yaitu (1) keharusan tindakan pemerintah, maupun (2) kebolehan perbuatan masyarakat secara riil untuk melakukan tindakan perlindungan hak kepada masyarakat adat dan sekaligus member peluang bergerak atau peluang bagi masyarakat adat untuk menjalankan apa yang menjadi bagian dari haknya. Prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang dikembangkan dengan bertolak dari penerapan tujuan-tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Menurut Souhaly (2006 : 76), hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam disekitarnya yang terlahir berdasarkan hukum adat merupakan suatu sistem tersendiri sejak leluhur (ancestral roots) yang memiliki efek praktis dan oleh karena itu memerlukan perlindungan hukum. Katakanlah perlindungan hukum riil terhadap hak-hak yang ada (the existing rights of indigenous people), perlu ditetapkan dan dijalankan secara administrative.
D. Penutup
Kebijakan pemerintah dalam pengaturan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih bersifat sentralistik dan mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Selain itu sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek hukum masih tumpang tindih atau bersifat kondradiktif. Terkait dengan wewenang antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat adat sistem hukum di Indonesia masih tetap mengatur dan mengakui eksistensi masyarakat hukum namun dalam implementasi belum memberikan perlindungan secara optimal.
DAFTAR BACAAN
Akimichi Tomoya, 1991, Teritorial Regulation in the Small Scale Fisheries of Ittoman, Okinawa,dalam Maritime Institution in the Western Pasific, Osaka: National Museum of Ethnology.
A.Wahyono, 1994, Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur : Hak Ulayat Laut di Sangihe Talaud – Studi Kasus Tentang Sistem Pengelolaan Sumberdaya Laut Pada Nelayan Pulau dan Nelayan Pantai, PMB-LIPI, Jakarta.
B. Riyanto, 2004, Pengaturan Hutan Adat di Indonesia – Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor,
B. Rudito, 1999, Peran Antropologi Dalam Pembinaan Masyarakat Terasing, Makalah Pada Seminar Jubelium ke-10 Jurnal Antropologi Indonesia, tanggal 6-8 Mei 1999.
Charles Zerner, 1993, Imaginating Marine Resources Management Institutions ini the Maluku Island, Indonesia 1870-1992, Workshop, Virgenia.
H. Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Penerbit UUI Press, Yogyakarta,
Hesty Irwan dkk, 2002, Aspek Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
Lawrence Friedman, 1975, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York.
Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Penerbit Citra Media, Yogyakarta.
Muhammad Yamin, 1971, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, Siguntang, Jakarta.
R.B. Pollnac, 1984, Investigating Territorial Use Right Among Fishermen, dalam Maritime Institutions in the Western Pasific, Osaka, National Museum of Ethnology.
Roberth Souhaly, 2006, Hukum dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Penerbit Unesa University Press, Jakarta.
R.Z. Titahelu, 1998, Makalah Tentang Hak-Hak Adat, Ambon,
——————, 2004, Legal Recognition to Local and/ or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People’s Self Confidence. Disampaikan pada kongres Internasional yang diselenggarakan oleh Commission of Folk Law and Legal Pluralism bekerjasama dengan University of New Brunswick, di Fredericton, New Brunswick, Canada, 26-29 Agustus 2004.
_____________, 2005a, Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum : Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku, disampaikan pada pengresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Agraria Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
______________, 2005b, Pembangunan Hukum Yang berkeadilan : Bahasan Hukum dan Masyarakat. Makalah disampaikan pada Konsultasi Gereja dan Masyarakat, diselenggarakan oleh Sinode AM Gereja-gereja di Sulawesi Utara dan Tengah – Tondano
Shidarta, Dietriec G, Bengen, Jacub Rais, Tommy H. Purwaka, M. Daud Silalahi, Sulaiman N. Sembiring, Rikardo Simarmata, Denny Karwur, R.Z. Titahelu, Aris Kabul Ptanoto, Jason M. Patlis, Etty R. Agoes, Hasjim Djalal, 2005, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, US Agency for International Development Coastal Resources Management Project II, Jakarta.
S. Soekanto, 1983, Beberapa Permaslahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
Sudo Ken Ichi, 1983, Sosial Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia dalam Kenneth Ruddle dan R.E. Johannes (eds) Traditional Marine Resources Management in Pasific Basin: an Anthropology, Jakarta, UNESCO/ROSTSEA.
[1] Tulisan ini diterbitkan dalam sebuah buku KOMPILASI PEMIKIRAN TENTANG DINAMIKA HUKUM DALAM MASYARAKAT (Memperingati Dies Natalis ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013), 2013
[2] Penulis adalah Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimuura, periode 2013 – 2017