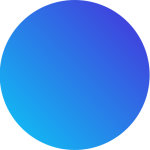Keadilan Restoratif dalam Budaya Orang Maluku
(Kajian dari Perspektif Hukum Pidana Adat)
Elsa R.M. Toule
1. Latar Belakang
Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters Tahun 2002[1] yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (a rational total of the responses to crime). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.
Keadilan restoratif (restorative justice) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.
Meskipun beberapa praktisi berpikir bahwa istilah yang tepat adalah pendekatan restoratif, tetapi keadilan restoratif merupakan istilah yang telah dikenal diberbagai belahan dunia. Konsorsium Restorative Justice, sebuah badan amal nasional di Inggris yang beranggotakan organisasi–organisasi nasional dan individu yang tertarik dalam mempromosikan keadilan restoratif, merumuskan:
Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. Itencourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives the man opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made. [2]
Marian Liebmann mengemukakan bahwa secara sederhana, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.[3]
Burt Galaway and Joe Hudson mengemukakan elemen–elemen yang fundamental dari keadilan restoratif, yakni: [4]
first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves;
second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute;
third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.“
Pendapat tersebut secara tegas menggambarkan bahwa persoalan tindak pidana bukan hanya melibatkan orang perorangan. Tindak pidana menimbulkan luka yang berpengaruh terhadap korban, masyarakat, bahkan pelaku itu sendiri, dan fungsi dari proses peradilan pidana bukanlah menghukum melainkan mendapatkan solusi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama–sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Tindak pidana menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi pulih dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.
Di berbagai belahan dunia, praktek penggunaan keadilan restoratif terhadap berbagai kasus telah diterapkan untuk berbagai kasus, sejaktahun 1970.[5] Dari perkembangan keadilan restoratif tersebut, terlihat bahwa pendekatan ini sudah digunakan bukan saja terhadap kasus yang melibatkan anak atau remaja, melainkan berkembang juga untuk kasus orang dewasa, termasuk di dalamnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restoratif sendiri mengandung prinsip–prinsip:
a. Membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, teman sebaya;
d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut; dan
e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.[6]
Keadilan yang restoratif adalah apabila proses pencapaiannya mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan baginya untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya, memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan masyarakat yang dirugikan.
Sebagai sebuah ide, keadilan restoratif layak mendapat ruang untuk terus berkembang. Paling tidak untuk saat ini. Tetapi ide ini tidak lahir dalam sebuah kevakuman sosial budaya. Legitimasi legal dan sosial telah terlanjur selama ratusan tahun memuja sistem yang retributif dengan kesetiaannya pada norma–norma dan struktur khas ‘legal-formal‘–nya.
Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif pada prinsipnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Para pihak (stake holder) adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak dengan tindak pidana yang terjadi. Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama para stake holder, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan timbul.[7]
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Maluku, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.
Penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat dengan media musyawarah baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.
Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan. Dari berbagai hasil penelitian di kepulauan Maluku menunjukkan bahwa Maluku sebagai kepulauan terbesar dengan 1.340 buah pulau kecil, dan luas lautnya yang dominan, yaitu 92% dan darat seluas 7,6%. Memiliki 117 sub etnik dan lebih kurang 120 bahasa daerah (etnik), sehingga menjadi sebuah cultur areal dengan keragaman sangat tinggi. Masing-masing memiliki cara pandang lokalnya dengan konsep-konsep lokal yang berbeda. Masing-masing menjalankan kehidupannya dengan falsafahnya. Orang Kei mengatur dan menyelenggarakan hidupnya dengan falsafah Kei, orang Seram dengan falsafah Seram, orang Ambon dengan falsafah Ambon, orang Buru dengan falsafah Buru, orang Aru dengan falsafah Aru dan sebagainya.
Dalam menyelenggarakan kehidupannya, masyarakat Maluku mengembangan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Meskipun terdapat hukum positif, realitas di Maluku menunjukkan bahwa di berbagai daerah masih dijumpai model penyelesaian sengketa menurut hukum adat, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau adat, pelaku dan keluarga serta korban dan keluarga. Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat di Maluku, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Meskipun terdapat banyak etnik, namun masyarakat Maluku memiliki satu falsafah budaya yang sama sebagai orang basudara. Falsafah budaya ini dikembangkan dan implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Model penyelesaian konflik dengan budaya orang basudara ini akan menghasilkan kesepakatan bersama diantara berbagai pihak terkait.
2. Hukum Adat, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Adat
Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa asing adatrecht. Adat bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Namun antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan, yaitu pada sumber dan bentuknya. Hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum dari masyarakat, sesuai dengan fitrahnya sendiri terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.[8]
Hukum adat bersifat turun temurun dari generasi ke generasi, yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tetap melembaga (diketahui, dipahami dan diterapkan) di dalam masyarakat. Dari aspek budaya, hukum merupakan bagian dari budaya, yang tumbuh dan berkembang serta berfungsi mengatur tata hubungan masyarakat.
Masyarakat memiliki kebudayaan, termasuk di dalamnya perangkat normatif atau pedoman untuk berperilaku dan bersikap. Pada saat penegakan hukum positif dilakukan, baru disadari bahwa ada keterbatasan dan kesenjangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan peluang untuk menggali esensi hukum yang bersumber pada hukum adat yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum sebenarnya berfungsi untuk melakukan keseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari beberapa budaya atau sub budaya terhadap yang lain, menjamin keadilan dan juga mengesahkan hubungan dominasi dari beberapa budaya atau sub budaya terhadap yang lain.[9] Sedangkan hukum adat sebenarnya memiliki kekuatannya dalam wujud realitanya sebagai pola perilaku (pattern of actual behavior). Pengkodifikasiannya menjadi pola untuk mengatur perilaku (pattern for behavior) akan menghilangkan kekuatan dinamikanya. Ter Haar memodernisasi hukum adat hanya dalam ihwal forum dan fungsinya, namun tetap menyerahkan modernisasi substansinya pada pengalaman masyarakat itu sendiri. Van Vollenhoven lebih melihat hukum adat sebagai “milik” rakyat, sedangkan ter Haar lebih melihat hukum adat sebagai bagian dari kebijakan penguasa. Konsep van vollenhoven memang lebih cocok dianut di masa hukum adat belum memperoleh pengakuan dan tak dipandang sebagai hukum yang memenuhi syarat untuk keperluan kehidupan modern.
Hukum adat tidak mengenal peraturan-peraturan prae exixtence, karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim menurut hukum adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan/hukum rakyat) bahwa perbuatan itu menentang hukum.
Dalam memahami hukum pidana adat, maka perlu untuk dikemukakan pengertian hukum pidana sebagai dasar untuk mengkaji eksistensi hukum pidana adat. Secara garis besar, dari berbagai pendapat tentang hukum pidana yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengandung adanya persyaratan tertentu, terisitmewa yang berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana bagi mereka yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut. Secara tegas, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana itu haruslah mengandung tiga hal penting, yakni adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, adanya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan adanya sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
Sedangkan hukum pidana adat dimaknai sebagai hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmos masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.[10]
Hukum pidana adat mempunyai sumber hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditataati oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan hukum tertulis adalah semua peraturan yang dituliskan baik di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.[11]
Hukum Pidana adat berlaku terhadap anggota masyarakat adat dan orang-orang yang di luarnya, yang terkait akibat hukumnya. Hukum Pidana adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan rohani.[12] Hukum pidana adat memiliki ciri tradisiona, karena pada dasarnya meliputi:
1. Adanya hubungan antara dunia nyata dan tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuatan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan;
2. Bukan merupakan hasil ciptaan pikiran rasional, intelektual dan liberal, tetapi justru merupakan hasil ciptaan pikiran yang komunal magis religious atau komunal kosmis.
Dengan memahami sifat hukum pidana tersebut, maka hal yang perlu mendapat perhatian adalah alasan diadakannya reaksi adat sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi. Menurut Hilman Hadikusuma, terdapat dua alasan sehingga dilakukan reaksi adat, yakni, tata tertib adat yang dilanggar dan keseimbangan masyarakat yang terganggu.[13]
Dengan demikian, maka inti pengertian hukum pidana adat adalah adanya pelanggaran atau delik atau perbuatan illegal yang akibatnya mengganggu keseimbangan atau kegoncangan dalam masyarakat. Akibat terganggungnya keseimbangan tersebut, maka patut diusahakan adanya pengembalian keseimbangan kembali melalui reaksi adat.
Jika dibandingkan dengan inti pengertian hukum pidana, maka pengertian tersebut tidak berbeda karena terdapat unsur:
1. Adanya perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, seperti perbuatan itu harus dilarang dan diancam oleh aturan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu; dan
2. Adanya pidana, yakni berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu tadi.[14]
Pendapat tersebut menyimpulkan bahwa hukum pidana adat mengandung pengertian ada perbuatan yang dilarang, ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, serta ada sanksi berupa pidana adat bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Keadilan Restoratifdan Hukum Adat di Indonesia
Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Eksistensinya diperkirakan sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri, bahkan di masa lampau, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan ini justru ditempatkan sebagai mekanisme utama.[15] Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dianggap sudah using, kuno dan tradisional kini justru dunyatakan sebagai pendekatan yang progresif.[16]
Konsep hukum adat sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif.
Soepomo mendeskripsikan ciri umum adat Indonesia sebagai berikut:
a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu persekutuan hukum;
b. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Eksistensinya dibatasi oleh batasan-batasan norma yang diterapkan baginya;
c. Tujuan persekutuan hukum masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir bathin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya (levemilieu).
d. Tujuan memelihara keseimbangan lahir bathin berangkat dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam semesta (kosmos). Ketertiban masyarakat merupakan bentuk harmonis antara segala sesuatu;
e. Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut.
Hukum adat memiliki mekanisme tersendiri dalam memecahkan persoalan berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat. Pelanggaran hukum adat mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Widnyana mengemukakan bahwa pelanggaran hukum adat merupakan:[17]
a. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat;
b. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;
c. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi;
d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali keseimbangan seperti keadaan semula.
Dengan demikian, pelanggaran hukum adat merupakan pelanggaran yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, Widnyana kemudian merumuskan sifat-sifat pelanggaran hukum adat sebagai berikut:
a. Menyeluruh dan menyatu
Sifat ini dilatarbelakangi oleh sifat kosmis yang menjiwai hukum adat, di mana satu hal yang satu dianggap bertautan dengan hal yang lainnya, yang mengakibatkan hal yang satu tidak adapat dipisahkan dari hal yang lain;
b. Terbuka
Ketentuan pelanggaran adat bermaksud mempertahankan rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat sesuai waktu, tempat, dan keadaan. Tradisi menurut hukum adat yang berlaku memang merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, tetapi dalam cara penyelesaian yang senantiasa bersifat terbuka;
c. Membeda-bedakan masalah
Penyelesaian pelanggaran adat melihat permasalahan tidak hanya dari perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang serta siapa pelakunya;
d. Peradilan atas permintaan
Pelaksanaan pemeriksaan perkara dalam pelanggaran hukum adat didasarkan atas ada/tidaknya permintaan dan pengaduan seseorang yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil;
e. Tindakan reaksi atau koreksi
Reaksi adat yang diambil berkenan dengan pelanggaran yang dilakukan tidak hanya terhadap pelaku semata-mata, tetapi juga dari anggota keluarga, kepada masyarakat yang bersangkutan, serta pengembalaian keseimbangan dengan mengadakan upacara adat.
Dalam pandangan hukum adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Penerapan sanksi adat adalah suatu upaya untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmis. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu.
Dalam bagian X dari Pandecten van het adatrecht dijelaskan bahwa sanski adat dapat berupa:[18]
a. Pengganti kerugian immaterial dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikasi gadis yang telah dicemarkan;
b. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
c. Selamatan untuk memberisihkan masyarakat dari kotoran gaib;
d. Penutup malu, permintaan maaf;
e. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.
Dalam hal demikian, unsur utama dari keadilan restoratif yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri hukum adat
4. Keadilan Restoratifdalam Budaya Maluku
Meskipun banyak keragaman yang dimiliki, namun orang Maluku masih bisa merangkai dan merangkul keberadaannya dalam sebuah kesadaran kolektif dan konsep diri sebagai orang basudara. Orang basudara merangkul dan menyatukan perbedaan dan membentuk diri sebagai sebuah masyarakat yang bersatu meskipun berbeda. Orang basudara adalah habitat asli orang Maluku, karena setiap masyarakat Maluku adalah pendukung komunitas orang basudara. Mereka mengoperasionalkan hakikat hidupnya itu dalam budaya hidop orang basudara sebagai sebuah karakter asli. Spirit hidop orang basudara itu nampak secara spesifik pada berbagai bentuk kekerabatan adat dan tradisi adat di wilayah kepulauan Maluku. Falsafah budaya Pela Gandong di Maluku Tengah sebagai satu sub zona makro kebudayaan Maluku, falsafah budaya Ain Ni Ain (budaya satu punya satu) di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, falsafah budaya Kai-Wai (budaya adik kakak) di Pulau Buru, falsafah Budaya Ursia-Urlim (kekerabatan adat kelompok dari dua leluhur bersaudara Ursia-Urlima di kepulauan Aru, falsafah budaya Duan Lolat (kekerabatan kelompok pemberi anak dara dan kelompok penerima anak dara) di Kepulauan Tanimbar, serta budaya Sioli Lieta Inanara (budaya hidup baik-baik bapa, mama, basudara laki-laki dan perempuan) di Maluku Barat Daya.
Budaya orang Maluku yang hidup sebagai orang basudara ini merupakan kearifan lokal di berbagai wilayah Maluku dapat menjadi pilihan utama, yang perlu digali dan dikembangkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, karena keadilan restoratif sebenarnya berakar dari kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki budaya musyawarah untuk mufakat, baik melalui sidang-sidang adat maupun dalam acara “kumpul sudara.”
Di Kepulauan Tanimbar, sumber materiil keadilan restoratif ditemukan dalam budaya Duan Lolat yang mengandung norma/nilai dari tradisi yang hidup di Kepulauan Tanimbar dalam mengatur “hubungan darah” dari sebuah perkawinan suami/laki-laki dan isteri/perempuan yang berlangsung terus menerus. Hubungan Duan Lolat memberikan makna:[19]
1. Solidaritas Sosial, bertumbuh dari kekeluargaan yang muncul lewat hubungan darah (darah sebagai lambang hidup) dari sisi perempuan. Untuk sisi iman (agama) dilihat dalam bentuk solidaritas adati yaitu mencintai, melayani, pengorbanan, nilai memberi hidup baik dalam kesusahan maupun kegembiraan ditanggung bersama.
2. Dimensi Persekutuan dalam keluarga, karena darah yang ditarik dalam suatu persekutuan dari dua keluarga menjadi satu. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita menarik kedua belah pihak ke dalam suatu ikatan kekeluargaan yang erat secara turun temurun, sehingga terjalin hubungan untuk saling bertanggungjawab, tercipta kerjasama dalam kehidupan bersama.
3. Nilai memberi hidup. Duan bertanggungjawab terhadap Lolat, merupakan kewajiban. Duan melindungi hidup, juga member hidup. Setiap nilai harus mengorbankan nilai-nilai lai, Duan bertanggungjawab terhadap Lolat sampai mati. Pemeliharaan dan penghargaan atas nilai hidup, Lolat wajib menjaga hidup yang berasal atau diberikan Duan, begitu sebaliknya.
Pada umumnya proses penyelesaian sengketa dalam budaya Duan Lolat, baik ketika terjadi masalah atau tindak pidana, apapun itu, berat atau ringan, maka masalah tersebut akan diselesaikan secara damai oleh tua-tua adat ataupun yang menjadi Duan, baik dari pihak korban maupun pelaku. Setelah masing-masing pihak berkumpul, diadakan upacara adat diawali dengan prakatan dan minum sopi. Kemudian membicarakan permasalahan yang terjadi untuk dicari inti persoalan yang jelas. Setelah proses berlanjut, diperoleh kesepakatan di mana masing-masing pihak merasa puas dannyaman, konsekuensi dari hasil pembicaraan akan dilaksanakan.
Selain Duan Lolat, sumber keadilan restoratif juga ditemukan dalam budaya Kalwedoyang memiliki nilai-nilai sosial keseharian, dan juga nilai-nilai religius yang sakral yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya Kalwedo mempersatukan masyarakat di kepulauan Babar maupun di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, yang mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai Kalwedo diimplementasikan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau dan negeri, yaitu: inanara ama yali (saudara perempuan dan laki-laki). Inanara ama yali menggambarkan keutamaan hidup dan pusaka kemanusiaan hidup masyarakat MBD, yang meliputi totalitas hati, jiwa, pikiran dan perilaku. Nilai-nilai Kalwedo tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup Niolilieta/hiolilieta/siolilieta (hidup berdampingan dengan baik). Tradisi hidup masyarakat MBD dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam kepulauan MBD.
Nilai keadilan restoratif di Maluku Tengah, ditemui dalam budaya Pela yang merupakan bentuk ikatan persaudaraandibangun oleh satu negeri dengan satu atau beberapa negeri lain dengan bentuk antara lain Pela Gandong, Pela Tampa Sirih, yang memiliki beberapa aturan dasar yang harus dipatuhi oleh warga suatu negeri yang terikat dalam hubungan pela. Ikatan pela ini kemudian menginspirasikan masyarakat Maluku untuk menganggap orang lain sebagai saudara, sehingga ketika terjadi konflik, maka spirit Pela ini akan menjadi panutan dalam menyelesaikannya.
5. Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia
Eksistensi hukum pidana adat dan semua yang melekat di dalamnya harus diletakkan secara proporsional dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena proses penegakan hukumnya yang melibatkan suatu lembaga yang berwenang harus dicari legitimasinya menurut hukum positif. Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia.
Faktanya, harus diakui bahwa masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi negara dalam menyediakan akses atas keadilan secara cepat dan terjangkau bagi masyarakat, terutama dikaitkan dengan keterbatasan akses keadilan melalui peradilan formal. Seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dan/atau marginal, atau pula masyarakat adat, untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi melalui institusi formal.
Di sisi lain, hidup di masyarakat secara turun temurun praktek peradilan rakyat, yang salah satunya adalah peradilan adat. Untuk memperkuat akses keadilan, maka didoronglah upaya memperkuat dan mendayagunakan alternatif lain dalam rangka mendapatkan akses keadilan di luar pengadilan formal.Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan peradilan informal (informal justice) dengan berbagai variannya seperti upaya mediasi (non-peradilan) dan penyelenggaraan peradilan adat. Dengan realitas konteks yang demikian, maka pertanyaan yang hendak dikaji adalah: Sejauh mana pembaruan kekuasaan kehakiman pasca 1998 (sebagaimana revisi UU Kekuasaan Kehakiman di tahun 1999, 2004, dan 2009) memberikan peluang dan akses keadilan bagi masyarakat adat dan institusi penegakan hukum lokal/adat. Ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.
Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia.[20] Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain:[21]
(a)Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
(b)Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau custom (kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih ‘steril’ keberlakukan sistem hukum formal.
(c)Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
(d)Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.
Kedua, pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.
Ketiga, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang yang sangat serius. Sebagai catatan, bila dilihat pada institusi tertinggi peradilan negara, data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa “setiap tahun ada 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun.”[22]Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara. Beban yang sedemikian berat ini tentu akan dapat dikurangi dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada peradilan adat agar dapat mengambil peran dalam upaya membuka akses keadilan yang lebih lebar bagi masyarakat penyelesaian konflik biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan teori universal dan mengadopsi dari luar, sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal (local wisdom).
Dalam masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan kedamaian, misalnya: Dalihan Natolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro (Jawa Timur), Alon-alon Asal Kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), Basusun Sirih (Melayu/Sumatera), dan Peradilan Adat Clan Selupu Lebong (Bengkulu).
Konsepsi awal mengenai masyarakat hukum adat sesungguhnya telah terdiskusikan lampau dan mengkristal di saat pembahasan dalam sidang BPUPKI, 10-17 Juli 1945. Ketika UUD 1945 diumumkan pada 23 November 1945, usaha pengakuan keberadaan daerah yang bersifat istimewa diakomodir dengan pengaturan dalam pasal 18. Dijelaskan di Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturende landschappen (atau istilah lain daerah-daerah swapraja) dan volkgemeenschappen. Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mengacu pada volkgemenschappen, bukan pada rechtgemeenschappen, sekalipun begitu terlihat bahwa fakta di lapangan ditemukan hukum adat, desa, nagari dan marga, serta persekutuan hukum lainnya.
Karena bentuk pengakuan yang demikian (volkgemenschappen), sesungguhnya pula berkonsekuensi terhadap pengakuan atas eksistensi sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang selama ini dijadikan acuan dan dasar dalam menuntaskannya, yakni sistem lokal yang bisa berupa peradilan adat. Sejarah konstitusi mengarah pula pada pergeseran arah pemikiran dari pasal-pasal konstitusinya, terutama berbasis Kostitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dapat pula disimak dalam ketentuan yang mengatur dasar konstitusional pemberlakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua pasal tersebut menyatakan: “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan menyebut aturan undang-undang dan aturan adat yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan.” Dengan pasal yang demikian, maka terjadi pergeseran, dari ‘daerah yang bersifat istimewa’ menjadi ‘daerah istimewa’. Ini artinya, lebih mengacu pada zelfbesturende landschappen, dan tidak mencakup volkgemeenschappen. Sekalipun demikian, konsep ini tak lama dipertahankan, karena sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain awal dari formasi Demokrasi Terpimpin ala Soekarno, konstitusi dikembalikan pada UUD 1945. Ini artinya kembali pada kosep semula awal negara Indonesia berdiri. Secara konseptual, tak lagi berubah hingga terjadi amandemen kedua tahun 2000, yang mengubah rumusan pasal 18, khususnya tambahan pasal 18B ayat (2), yaitu, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Selain itu, dalam amandemen kedua pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dirumuskan konsep hak asasi manusia yang menegaskan soal identitas budaya dan hak tradisional, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal ini berkait erat dengan bunyi amandemen keempat, Pasal 32 ayat 1 dan 2: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
Bila ditilik dari rumusan kedua pasal tersebut, maka pengakuan negara meliputi kedua aspek pengakuan, baik terhadap persekutuan hukum maupun persekutuan masyarakatnya. Di dalam konsep itu, maka nampak terjadi percampuran konsep, yang menggabungkan antara konsep rechtgemeenschappen dan volkgemeenschappen. Selain itu, satu hal yang menarik bila ditempatkan dalam konteks politik amandemen kedua, pembahasan kedua pasal itu lebih memperlihatkan dimensi pengakuan dan penghormatannya dari sudut pandang hak asasi manusia.
Daftar Pustaka
[1] United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.Vienna:UN.2002.
[2] Restorative Justice Consortium(2006) Leaflet.London:RJC.Retrievedfromhttp://www.restorativejustice.org.uk,<10Nov.2010>.
[3] Marian Liebmann, RestorativeJustice,HowitWorks,JessicaKingsleyPublisher,Londonand Philadelphia,2007,hal.25
[4] Burt Galaway and Joe Hudson dalam, John Braithwaite(ed), Restorative Justice & Responsive Regulation, Oxford University Press,Inc.,NewYork,2002, hal.8.
[5] PaulMcCold, ”TheRecentHistoryOfRestorativeJustice,Mediation,Circles,andConferencing”, dalam DennisSullivanandLarryTifft,HandbookofRestorativeJustice,aGlobalPerspective,Routledge,Taylorand FrancisGroup,NewYork,2006,hal.35
[6] Marilyn Fernandez Restorative JusticeforDomesticViolenceVictims,AnIntegratedApproachtoTheir HungerforHealing,LexingtonBooks,UnitedKingdom,2010,hal.151.
[7]UnitedNationsCommissiononCrimePreventionandCriminalJustice,BasicPrinciples, Op. Cit.
[8] Soepomo, Bab-bab Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 7
[9] Ronny H. Soemitro, Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum, BP UNDIP, Semarang, 1988, hal 73
[10] I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana, Eresco, Bandung, 1993, hal 3
[11] Ibid hal.6
[12] Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984, hal. 29-30
[13] Ibid, hal. 15
[14]Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 9
[15] Eva A. Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung Bandung, 2011, hal. 67
[16] Marc Levin, Restorative Justice in Texas, Present and Future, Texas Public Policy Foundation, Texas, 2005, hal 5-7
[17] Widnyana, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1995, hal 5
[18] I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa ke Masa, Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 5
[19] Melania S.F.H. Usmany, Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Lolat di MTB sebagai Sarana Non-Penal, Tesis, UNDIP Semarang, 2010.
[20] Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.
[21] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm. 182 – 203
[22] Diakses dari http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/ tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?