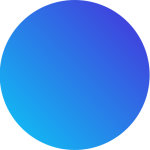Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis[1]
———————————————–
Elsa R. M. Toule
1. Pengantar
Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.
Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.[2] Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.
Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.[3]
Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Di Tahun 2007, dari 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 17.722 kasus atau 69,6 persen adalah kekerasan terhadap isteri.[4] Pada tahun 2008, angka ini meningkat lagi menjadi hampir 86 persen yakni sebanyak 46.884 dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 54.525.[5] Data KDRT 2010 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap istri tahun 2009 adalah sebesar 96 persen dari seluruh jumlah KDRT, yakni 131.375 kasus.[6] Selain istri, anak perempuan juga menjadi korban terbanyak dari KDRT. Pada kasus KDRT dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya.
Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau isteri menjadi korban yang paling dominan dalam KDRT, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman?
2. Pengertian dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: “Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.”
Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
Anne Grant mendefisinsikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (assaultive) dan memaksa (corsive), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.[7] Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri)
Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.
Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka UU PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam UU PKDRT.
Pengakuan UU PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PKDRT).
Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur KDRT an sich namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 UU PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.
Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.
3. Ruang Lingkup KDRT
UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-undang ini, selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.
4. Pemulihan Korban KDRT
UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.
Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran. Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.
5. Kewajiban Masyarakat
Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk
a) mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b) memberikan perlindungan kepada korban;
c) memberikan pertolongan darurat; dan
d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak kepolisian,. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.
6. Faktor Penyebab terjadinya KDRT
Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.[8]
Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan memengaruhi anggota keluarga yang lain.[9] Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Wakil Ketua Komnas HAM, bahwa faktor dominan antara lain budaya partiarki, budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasikan perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti melihat KDRT lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri.[10]
Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni : [11]
a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami
b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.
d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.
Di samping itu, secara mikro (keluarga-kelompok masyarakat), sejumlah faktor diidentifikasikan dapat menjadi pendorong (pemicu dan pemacu) meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT, antara lain :
a. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan;
b. Semakin langkanya tokoh panutan yang menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c. Banyaknya tayangan di media massa (terutama televisi) yang menampilkan berita atau video (film dan sinetron) tentang tindakan kekerasan;
d. Sikap dan penampilan perempuan yang semakin berani. Berjalan di malam hari, di tempat rawan, dan berpenampilan berani, baik di tempat umum maupum media massa.
e. Pemberitaan tindak kekerasan yang dipublikasikan terlalu vulgar (bebas) di media massa yang dapat memacu perilaku publik bahwa tidak kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di mana-mana.
Selain itu, teridentifikasi juga beberapa faktor lain yang turut memengaruhi, teristimewa untuk daerah Maluku dan Papua seperti pembayaran mahar dan kebiasaan minum minuman keras.
Banyak faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.
Pertama dan yang utama adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.[12]
Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja.
Keempat, keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT.
Kelima, mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.
Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.
7. Penutup
Menghadapi kasus KDRT yang meningkat dari waktu ke waktu, maka berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama. Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom), di atas semua itu. adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran agama yang baik dan benar.
[1] Disampaikan pada Kegiatan Workshop Pelatihan Hukum dan HAM, Departemen Pelpem Sinode GPM, Ambon, 18-19 Juli 2012.
[2] Kathleen J. Ferraro, “Woman Battering : More than Family Problem,” dalam Women, Crime and Criminal Justice, Ed, Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California 2001, hlm. 135.
[3] Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
[4] Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2008
[5] Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2009
[6] Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2010
[7] Anne Grant, Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010.
[8] Ciciek Farha, dalam Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 35.
[9] Wawancara dengan Estoe Rakhmi Fanani, SPi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan-Jakarta (LBH APIK), Jakarta, Juli 2010.
[10]Yoseph Adi, Wakil Ketua Komnas HAM ,wawancara, Jakarta, Juli 2010.
[11] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008, hlm. 28-29.
[12] Komnas Perempuan, Referensi bagi…. Op cit, hlm. 35.