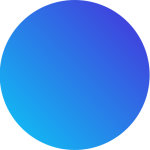Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU TP Korupsi
Elsa R.M. Toule[1]
A. Pengantar
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dirumuskan bahwa kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.[2] Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan antara lain untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.
Perumusan yang demikian mengindikasikan bahwa korupsi merupakan masalah nasional yang proses penanggulangannya terus diupayakan, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembaruan materi hukum, dalam hal ini peraturan undang-undangan. Hal ini menjadi penting mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspek, dan proses penanggulangannya telah dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, diantaranya ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.
Perumusan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu menjadi polemik yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ancaman pidana mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya tidak bermakna apapun karena penerapannya diabaikan oleh aparat penegak hukum.
B. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.
Secara tegas hal tersebut diakui dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi ini yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengupayakan berbagai upaya pemberantasan korupsi.
Transparancy International mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/ CPI) di tahun 2010 adalah sebesar 2,8 dan menduduki ranking 110 dari 178 negara, Tahun 2011 mencapai 3,0 dan menduduki ranking 100 dari 183 negara. Sedangkan di tahun 2012, CPI Indonesia mencapai 3,2 namun turun peringkat menjadi 118 dari 182 negara.[3] Korupsi dilakukan dalam berbagai sektor, yakni dalam penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, APBN/APBD, DAU/DAK/Dekonsentrasi. Beberapa kasus menonjol (celebrity case) yang mendapat perhatian besar masyarakat, dan membutuhkan upaya dan kerja keras aparat penegak hukum untuk mengungkapkannya adalah antara lain kasus korupsi pajak, proyek Hambalang, simulator SIM, dan import daging sapi, yang melibatkan pegawai pajak, anggota DPR, pejabat Polri, petinggi partai politik, bahkan menteri.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi penggangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam. Diperkirakan Angka Kemiskinan di Indonesia menurut BPS, Maret 2012 adalah sebesar 29, 13 juta orang atau 11,96%; jumlah pengangguran adalah sebanyak 7,6 juta orang; Hutang luar negeri berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2012 adalah 1.937 triliun. Pinjaman sebesar 615 triliun, dan surat hutang sebesar 1.322 triliun. Sedangkan kerusakan hutan adalah seluas 3.8 juta hektar, yakni yang dibabat dan dieksploitasi secara illegal. Kondisi ini dengan sendirinya menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditanggulangi dengan cara-cara yang ekstra.
C. Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam UU Pemberantasan TP Korupsi
Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.
Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati;
1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.
Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[U1]
Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti dikemukakan di atas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia[U2] . Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.
D. Pidana Mati bagi Koruptor dalam Ius Constituendum
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa,” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.
Berdasarkan realita tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, masih relevankah merumuskan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Hal ini didasarkan pada wacana perlunya merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena masih memiliki kelemahan, antara lain belum ada ketentuan yang mengatur tentang grativikasi seksual, dan ketentuan pembuktian terbalik yang hampir tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Selain itu, pidana mati masih tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-undang KUHP dengan sifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif[U3] .[4]
Pertanyaan ini tidak akan terjawab hanya dengan menentukan secara jelas syarat-syarat yang menyebabkan seorang koruptor dapat dipidana mati, melainkan pengkajian terhadap pentingnya menjatuhkan pidana mati bagi koruptor dari sudut pandang tujuan pemidanaan.
Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Catatan: Pelanggaran HAM. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.[5]MUI tidak menerangkan juga bahwa dalam hukum Djinayah (hukum syariah) terdakwa yang diancam pidana mati dapat membayar diyat (uang santunan) dan memperoleh ampunan dari keluarga korban, tidak dipidana mati[U4] .
Kedua pernyataan di atas secara tegas mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah sesuatu yang secara dikotomi harus dipertentangkan dengan hak untuk hidup sebagai non-derogable right dari sudut hak asasi manusia. Meskipun demikian, perdebatan tentang pidana mati akan tetap dilakukan, karena secara konstitusional, UUD RI 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan karena itu, pengambilan hak hidup seseorang, apapun bentuknya merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.[U5]
Perdebatan tentang pidana mati juga tetap beralasan, karena realitanya, secara internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB telah mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya mendorong penghapusan pidana mati, antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang hak-hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati.
Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak jaman Cesare Beccaria di sekitar tahun 1780, yang pernah menyatakan menentang hukuman mati karena dianggap tidak mahusiawi dan tidak efektif.[6] Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan (korupsi)? Terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang menentang (abolisionis) maupun yang mendukung (retensionis) hukuman mati.
Kelompok abolisionismendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding resolutions) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati.
Kelompok abolisionis juga menolak alasan kaum retensionisyang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2), dan Swedia (4).
Sementara itu, kelompok retensionis mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati, pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang. Bandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.[7]
Kelompok retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati (terhadap koruptor) bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis, justru korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara de yure maupun de facto mengakui adanya pidana mati. [U6] Kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.[8]
Dasar argumentasi dari kedua kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya hanya dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling jahat dan berdampak luas, dan perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya. Selain itu, hukuman mati harus sangat hati-hati untuk dijatuhkan.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang aparat penegak hukumnya sering terlibat korupsi seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (miscarriage of justice). Karena itu, untuk mencegah miscarriage of justice terdakwa korupsi harus diberikan hak melakukan upaya hukum yang adil. Dan jika akhirnya dipidana mati, terpidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi atau mendapatkan pemberlakuan sifat khusus dari pidana mati tersebut, seperti yang dirumuskan dalam konsep KUHP nasional.
E. Penutup
Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Suatu peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang baik hanya akan menjadi kata-kata mati jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.
[1] Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon
[2]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
[3] Abraham Samad, Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah, Simposium Nasional Rekonseptialisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, MAHUPIKI-FH UNHAS, Makassar, Maret 2013
[4] Rancangan undang-undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, 11 Desember 2012
[5] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Jakarta, 28 Juli 2005
[6] Beccaria, Of Crime and Punishment, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, hal. 9.
[7] United Nations, World Drug Report. 2012. United Nations Office On Drugs And Crime. Vienna, New York, 2012.
[8] Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, , Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24