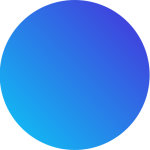HAK PETUANAN LAUT DI MALUKU[1]
S.E.M. Nirahua[2]
A. Pengantar
Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam perubahan kedua UUD 1945 diatur secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3). Pengaturan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.
Perubahan kedua UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi sekarang ini menjadi salah satu agenda nasional. Pengaturan ini diharapkan akan mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan pengaturan baru yang di dalamnya mengatur pengakuan dan penghormatan dari negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang ada diberbagai daerah yang hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat (di Maluku dikenal dengan Hak Petuanan). Pemberian pengakuan dan penghormatan ini tidak berarti adanya kebebasan dan peluang bagi masyarakat hukum adat untuk hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengakuan dan penghormatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2) diatur secara limitatif dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) terutama pada rumusan ”sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”. Rumusan ini dimaksudkan sebagai syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dihidup-hidupkan. Selain itu tentu saja dengan suatu pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.
Selama ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, tetapi masalah hak petuanan laut belum terlalu menjadi konsern bersama. Hak-hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak petuanan laut hanya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739. Namun pengaturan dalam undang-undang tersebut pun belum secara langsung memberikan pengaturan adanya hak petuanan laut, tetapi lebih menekankan pada unsur mempertimbangkan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603, tidak sama sekali mengakomodir kepentingan pengelolaan laut berdasarkan hak ulayat laut masyarakat hukum adat. Dampak dari tidak adanya pengaturan ini akan merugikan masyarakat hukum adat yang secara turun temurun telah memiliki hak-hak tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut di Provinsi Maluku. Tidak adanya dasar legalitas pengaturan wewenang masyarakat hukum adat ini pun merupakan bagian dari pembatasan terhadap hak-hak dan wewenang masyarakat hukum adat itu sendiri.
B. Konstitusionalitas Masyarakat Hukum Adat
Paradigma ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya Perubahan UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sebelumnya, rumusan masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam UUD 1945 hanya dikenal terminologi ”hak-hak asal-usul” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan).
Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa ””Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa”. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa :
I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “eenheidsstaat“, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat “Staat” juga.
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
Di daerah-daerah yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan ”Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.
Berkaitan dengan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, nampak adanya pengakuan Negara terhadap ”otonomi asli” berdasarkan hak asal usul. Susunan asli memiliki keistimewaan dengan susunan asli dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah besar dan kecil diberikan status otonom atau administratif. Dalam hal ini, otonomi asli merupakan hak asal usul yang masih ada dan dipraktekkan. Keberadaan Negara terhadap hak asal usul ini dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap sesuatu yang telah ada sebelum adanya Negara. Otonomi daerah merupakan pemberian negara yang bersifat administratif untuk memberikan keseimbangan politik hubungan pusat dan daerah.
Pengakuan terhadap otonomi negeri (baca: desa) merupakan bentuk politik hukum pemerintah (founding fathers) dalam Pasal 18 UUD 1945. Pengakuan terhadap hak asal usul bermakna yuridis bahwa hak asal usul ini merupakan hak yang melekat pada sejarah asal usul masyarakat. Hak asal usul ini adalah hak bawaan (bukan hak pemberian) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat. Dalam konstruksi hukum demikian, suatu pengakuan dari negara yang memiliki otoritas tertinggi kepada masyarakat hukum adat didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat hukum adat itu memiliki keistimewaan tertentu yang telah ada sebelumnya dan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hak bawaan masyarakat hukum adat ini salah satunya merupakan hak ulayat atau hak petuanan.
Dari makna filosofis Pasal 18 UUD 1945 dan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak-hak asal-usul yang dimiliki. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai volksgemeenschappen merupakan susunan asli yang memiliki hak-hak asal usul. Hak-hak asal usul ini tentunya merupakan hak-hak yang telah ada dan dipraktekkan sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda. Pengakuan juridis terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebelum adanya UUD 1945 diatur dalam Pasal 118 juncto Pasal 128 I.S. bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan) yang dilanjutkan dengan pengaturan dalam Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) Lembaran Negara 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 Lembaran Negara 1938 Nomor 681.
Tentunya pengakuan dalam Pasal 18 UUD 1945 merupakan upaya penghormatan terhadap hak-hak asal usul yang telah diatur sebelumnya, dengan asumsi bahwa kehidupan masyarakat hukum adat telah ada sebelum adanya negara Republik Indonesia. Hal ini tentunya patut dikemukakan bahwa volksgemeenschap bukan merupakan suatu pemerintahan bentukan atau ciptaan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan koloniah, dan karena itu pun dalam unifikasi hukum Indonesia, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menjembatani hal tersebut.
Dalam perkembangannya setelah perubahan UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini pun diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Dari rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di atas, masyarakat hukum adat memiliki legalitas berupa pengakuan dan penghormatan dari negara. Pengakuan dan penghormatan ini pun berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Berbicara mengenai hak konstitusional, maka hal ini berkaitan dengan segala hak yang dimiliki oleh warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Demikian, masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara pun memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.
Perubahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MPR RI) dilatar belakangi oleh satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) negeri (di Ambon) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.
Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa:
”Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa; dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Secara umum, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan peluang dan kesempatan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Namun, di lain pihak, pengaturan ini memberikan pembatasan yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.Adanya pengakuan dari negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, ditemukan dalam rumusan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Pengakuan dan penghormatan ini merupakan wujud dari era reformasi yang memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat melalui konstitusi. Hal ini sebagai akibat adanya sentralisasi yang dilakukan pada masa Orde Baru yang mengedepankan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sentralisasi ini berakibat pada hilangnya identitas masyarakat hukum adat yang dilakukan dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
C. Syarat Eksistensial Masyarakat Hukum Adat
Pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan starting point bagi adanya masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.
Sementara itu, rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini pun memberikan batasan yang merupakan syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan ”sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Rumusan ini dengan sendirinya memberikan batasan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya. Melalui rumusan tersebut, suatu masyarakat hukum adat harus memiliki syarat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.
Berkaitan dengan adanya pembatasan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, R. Yando Zakaria menyatakan bahwa:
”…adanya perumusan ’negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (seperti desa, Nagari, Banua, huta dll., misalnya) beserta hak-hak tradisionalnya (hak-hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, seperti ’sebelum adanya negara’)’, sebagaimana yang sering disuarakan oleh pendukung gerakan masyarakat adat dan otonomi desa selama ini, masih ada dua jebakan lain. Pertama, siapa yang akan menentukan masyarakat hukum adat itu ’masih ada’ dan ’sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat’ itu?; kedua, ukuran-ukuran apa saja yang akan digunakan untuk menentukan masyarakat hukum adat itu masih ada dan masih sesuai atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat?
Lebih lanjut R. Yando Zakaria mengemukakan bahwa :
”Namun, khususnya berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, malah yang lebih penting dari kedua masalah di atas adalah telah diubahnya perumusan – dan/atau keberadaan – ’hak asal usul’ pada pasal 18 UUD 1945 menjadi sekedar “ hak-hak tradisional” pada pasal 18B UUD 1945 ayat (2) itu . Dengan perumusan yang demikian, pengakuan hukum dan politik dari satuan-satuan masyarakat hukum adat – sebagaimana yang terkandung dalam konsep “hak asal-usul” – dirubah menjadi sekedar pengakuan terhadap tradisi dari masa lampau, yang dapat saja disingkirkan jika dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Padahal keharusan bagi pengakuan atas hak hak masyarakat hukum adat tidak terletak pada keaunikan tradisi masa lampau, melainkan terletak pada pengakuan atas hak masyarakat adat untuk mengatur kehidupannnya sendiri dalam konteks waktu saat ini sekalipun.
Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat setelah adanya pemenuhan terhadap syarat eksistensial telah diatur secara jelas dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang mengatur bahwa ”kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional”. Dalam Pasal 97 ayat (2) diatur syarat yang harus dipenuhi antara lain (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat.
Syarat eksistensial ini bersifat alternatif yang dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat berdasarkan susunan asli dan hak asal usul untuk ditetapkan sebagai Negeri (baca: Desa Adat). Pemenuhan terhadap syarat eksistensial ini akan melahirkan kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya. Legalitas adanya pengakuan dan penghormatan oleh negara setelah adanya penetapan Negeri dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
Aspek yuridis lainnya terkait dengan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Apabila masyarakat hukum adat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka masyarakat hukum adat memperoleh hak pengakuan dan perlindungan oleh Negara. Persyaratan dimaksud antara lain: (a) sejarah masyarakat hukum adat; (b) wilayah adat; (c) hukum adat; (d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Legalitas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini setelah adanya penetapan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
D. Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat di Maluku
Hak petuanan laut atau hak ulayat laut (marine tenure) di Maluku berkaitan dengan konsep pemilikan. Pemahaman tentang hak petuanan laut (marine tenure) apabila dikaitkan dengan hak petuanan laut yang di Provinsi Maluku, maka konsep pemilikan tercermin dalam “wilayah petuanan laut” yang dari aspek konsep batas (boundaries) menunjukan batas-batas wilayah petuanan yang tidak jelas. Dengan kata lain bahwa hak petuanan laut sebagai sebuah konsep kepemilikan oleh masyarakat hukum adat jelas memang ada dan diakui. Namun perbedaan persepsi tentang batas wilayah petuanan laut yang di dasarkan pada pemahaman yang berbeda antara masyarakat di masing-masing Negeri merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri.
Batas wilayah petuanan laut ditentukan dalam dual hal, antara lain batas petuanan laut antar negeri dan batas petuanan laut negeri dan laut lepas. Konsep batas petuanan laut antar negeri merupakan garis imajiner yang ditarik dari batas petuanan darat ke arah laut. konsekuensi dari garis imajiner ini, maka penentuan batas wilayah petuanan cenderung bersifat subjektif berdasarkan perkiraan. Mengenai batas wilayah petuanan negeri dengan laut lepas sebagai laut milik umum (common property/public property) merupakan garis imajiner yang berada antara laut dangkal (disebut laut putih atau saaro) dan laut dalam (laut biru).
Beberapa karakteristik petuanan laut Negeri, diantaranya:
a. Hampir di semua Negeri diakui bahwa batas ini tidak berlaku bagi nelayan yang melakukan kegiatan mencari ikan. Bagi mereka wilayah kegiatan perikanan tidak dibatasi, tergantung pada sejauh mana mata memandang atau kemampuan para nelayan untuk mendayung.
b. Bagi Negeri-Negeri yang wilayah laut (labuannya) merupakan teluk, maka teluk tersebut dianggap sebagai wilayah petuanan laut, tanpa memperhitungkan batas air putih dan air biru.
c. Beberapa Negeri mengakui wilayah petuanan laut atas perairan-perairan dangkal yang berada di tengah laut yang disebut saaro atau meti.
d. Jalur laut antara Negeri dengan pulau pulau kecil yang berdekatan dengannya, dimana pada jalur-jalur laut tersebut bagi orang-orang yang bukan anak Negeri hendak memasang rumpon (sero gantung) harus memperoleh izin dari Negeri yang mengklaim jalur laut tersebut sebagai wilayah petuanan lautnya.
Dalam wilayah petuanan laut Negeri, terletak hak kepemilikan dan pengelolaannya. Hak ini bersifat eksklusif dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai kepemilikan bersama. Sebagai contoh di Negeri Nolloth dan Negeri Haruku dikenal dengan ”Labuhan Sasi” yaitu wilayah yang sangat eksklusif pada saat-saat tertentu bersifat tertutup bagi siapapun termasuk bagi anggota masyarakat Negeri yang bersangkutan. Labuhan sasi ini ditetapkan oleh Pemerintah Negeri agar sumber daya alam di laut tidak dieksploitasi.
Adanya jaminan konstitusional dan legalitas bagi masyarakat hukum adat di Maluku dalam pengelolaan wilayah petuanan laut harus dibarengi dengan pengaturan bersifat tertulis. Konsep pengelolaan wilayah petuanan laut lebih didasarkan pada konsep oral (lisan) seyogyanya ditransfer menjadi konsep tertulis agar adanya pengakuan dan perlindungan dari Negara.
Dalam kaitan dengan pemenuhan syarat eksistensi masyarakat hukum adat terhadap wilayah petuanan laut, saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603). Undang-Undang Kelautan yang lebih berorientasi pada pengelolaan kelautan termasuk sumber daya kelautan tidak memberikan jaminan terhadap masyarakat hukum adat atas wilayah petuanan laut. Penormaan dalam Undang-Undang Kelautan tidak mengatur hak masyarakat hukum adat, namun mengharuskan partisipasi masyarakat dalam merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal (Pasal 70 ayat (4)). Pengaturan ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa yang telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya.
Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, diperlukan adanya Peraturan Negeri yang mengatur batas wilayah petuanan laut dan kewenangan pengelolaannya. Kebutuhan adanya peraturan negeri ini telah memperoleh delegasi kewenangan perundang-undangan dalam Undang-Undang Desa yang didasarkan pada hak asal usul masyarakat hukum adat.
Daftar Bacaan
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003.
2. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
3. R. Yando Zakaria, Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa, LAPERA Pustaka Utama berkejasama dengan KARSA, Yogyakarta, 2004
4. Wahyono, Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia, Media Pressindo, Jakarta, 2000.
[1] Makalah Disampaikan Pada FGD Pengakuan, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Atas Hukum Adat, Kerja Sama Program Pascasarjana Unpatti Dengan Komisi Ilmu Sosial Akademi Pengetahuan Indonesia (AIPI), 29 Maret 2016, Di Swissbel Hotel, Ambon
[2] Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura