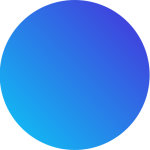EKSISTENSI OTORITAS ADAT DALAM PERADILAN INFORMAL PADA RECHTSGEMEENSCHAP LILIALI KABUPATEN BURU (RECHTSGEMEENSCHAP JUDICIAL AUTONOMY STUDY)
Oleh: Arman Anwar[*]
Abstrak
Informal system of judicature as institution of law in local storey which has been practice hereditaryly, if can be powered expected to become best solution as one of mechanism solving of dispute alternative, remembers the institution has some comparability excellences. This thing means can lessen work load from formal jurisdiction because as it is known that by the end of the year 2007 only, population of case circulating in Appellate court, has reached 20319 cases consisted of by Active Case 13525 cases ( 67%) and case which its(the age to 2 year 6794 cases ( 33%).
Federation public of customary law Liliali has a number of choices solving of conflict when they disagree. They tend to chooses informal system of judicature because this mechanism without cost, quicker, flexible and easier to be accessed compared to formal system of judicature.
Custom authority existence in informal system of judicature influenced by level of trust of ability public would of Raja and Saniri Besar in deciding a case. Prima service aksesibility, consistency and quality of decision confessed enough giving satisfaction for all the lawsuit, and authority and wide knowledge in comprehending case of lawsuit is factor strengthening their integrity and kapability.
Excellence of comparability inheren from custom authority existence in informal system of judicature at rechtsgemeenschap Liliali is ( source of lives of either symbolically and and also realist) for Kabupaten Buru and Indonesian nation generally
Key word : custom authority existence, informal system of judicature and lebenstraum
I. Pendahuluan
Kabupaten Buru termasuk salah satu kabupaten yang ada di Provonsi Maluku. Masyarakatnya dikenal karena adat dan budayanya yang kuat dan spesifik. Adat istiadat masyarakat Buru dapat terlihat dari adanya persekutuan hukum adat (Rechtsgemeenschap) yang tetap hidup dan diakui sebagai pranata dalam masyarakat. Sehingga selain ada wilayah administrasi pemerintahan daerah, juga terdapat wilayah adat yang terhimpun dalam 8 (delapan) Rechtsgemeenschap dimana masing-masing Rechtsgemeenschap tersebut dipimpin oleh seorang Raja. Adapun kedelapan persekutuan hukum adat (Rechtsgemeenschap) tersebut terdiri atas Lisela, Tagalisa, Liliali, Kayeli, Waesama, Masarete dan Fogi serta Ambalau. (Peraturan Bupati Buru Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Tahun 2007-2012, Op Cit, hlm 10)
Rechtsgemeenschap Liliali sebagai salah satu Rechtsgemeenschap yang ada di Kabupaten Buru. Memiliki wilayah petuanan (Rechtsgemeenschap) tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Namlea dan Kecamatan Wablau, meliputi 16 desa dan 13 dusun, secara geografis terletak di Pulau Buru Utara Timur. Persekutuan hukum adat Liliali juga sempat termarginalisasi sebagai imbas berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang telah menyeragamkan struktur pemerintah desa diseluruh Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ditegaskan bahwa pengaturan mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, lebih lanjut di atur dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dilain pihak, penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai Desa atau dengan nama lain sesuai tradisi adat-istiadat yang berlaku di Kabupaten Buru juga belum ada.
Atas dasar tersebut maka pengaturan mengenai desa atau dengan nama lain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru menjadi urgen karena (1) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang merupakan Perda Payung (Umbrella Provision), (2) Belum adanya aturan hukum yang jelas mengatur mengenai Negeri di Kabupaten Buru sebagai tindak lanjut dari Perda Propinsi. Untuk itu perlu adanya Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Payung (Umbrella Provision) Perda Propinsi. Hal ini disebabkan Peraturan Daerah Propinsi hanya mengatur hal-hal pokok saja sedangkan setiap kabupaten mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten tersebut mengatur tentang pemberlakuan sistem pemerintahan Negeri sesuai adat dan tradisi pada negeri-negeri di Kabupaten Buru dan disesuaikan dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Penyusunan peraturan daerah mengenai Negeri di Kabupaten Buru, dianggap sangat penting dan mendesak guna menata kembali Pemerintahan Negeri sesuai adat masyarakat Buru, termasuk dalam pengertian tersebut adalah tentang otoritas adat dan akses mereka didalamnya.
Sinkronisasi antara situasi normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosiologis dalam hal sosial budaya maupun adat istiadat mutlak diperlukan agar tidak timbul Anomic Society dalam masyarakat akibat tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum maupun adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk itu penulisan ini dilakukan berdasarkan pada pendekatan Rechtsgemeenschap Judicial Autonomy Study (RJA) di Rechtsgemeenschap Liliali di Kabupaten Buru.
II. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang memadukan pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskripsi terhadap berbagai masalah yang ada didalam peradilan informal pada Rechtsgemeenschap Liliali melalui pendekatan Rechtsgemeenschap Judicial Autonomy Studi (RJA) dan dalam konteks Rechtsgemeenschap yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.
b. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Rechtsgemeenschap Liliali Kabupaten Buru, dengan fokus perhatian pada struktur adat istiadat yang berkaitan dengan otoritas adat dalam peradilan informal dan eksistensinya pada Rechtsgemeenschap tersebut.
c. Penggunaan dan Teknik Pengambilan sampel.
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh desa yang ada pada Rechtsgemeenschap Liliali Kabupaten Buru. Sampel dari penelitian ini akan ditentukan dengan mengunakan teknik purposive random sampling.
d. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data primer (adat istiadat dan hukum adat), alat yang digunakan adalah kuesioner dengan sistem terbuka yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan wawancara secara terstruktur dan mendalam. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum didapat melalui penelusuran kepustakaan terkait dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.
e. Metode dan Teknik Pengolahan Data
Data yang terkumpul kemudian diedit, diklasifikasi dan dianalisis. Analisa yang dipakai adalah analisa kualitatif normatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta maupun data-data lapangan, kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan maupun aturan hukum positif yang berlaku.
III. Permasalahan
Untuk dapat memberikan penguatan lebih serta untuk mendorong terbentuknya Ranperda tentang Negeri yang sesuai dengan kondisi karakteristik masyarakat adat di Buru dan peran penting otoritas adat dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakatnya maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana eksistensi otoritas adat dalam sistem peradilan informal pada Rechtsgemeenschap Liliali dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di Kabupaten Buru.
III. Pembahasan
A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT BURU
1. SEJARAH TERBENTUKNYA SUSUNAN MASYARAKAT ADAT BURU
Van Vallenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adatrechts van Nederlands Indie deel I, 1906-1918, membagi wilayah hukum adat Indonesia atas 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (adatrechtskringen). Adapun Buru, oleh Van Vallenhoven dimasukan kedalam lingkungan hukum adat yang ke 13 bersama-sama dengan Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Kisar. (Prof Busrah Muhammad, S.H., Op Cit, hlm 94)
Ter Haar menyebutkan Buru kurang lebih 3 (tiga) kali dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Menurutnya, bahwa masyarakat pedalaman Buru adalah golongan yang mendiami suatu wilayah (teritorial) yang terbatas dan kemudian berinteraksi dengan bagian-bagian dari klan tetangga melalui perkawinan exogami. (Exogami artinya kawin dengan wanita dari luar klan sendiri. klan dari pihak istri akan melepaskannya dari ikatan kekeluargaannya dan secara otomatis istri masuk kedalam lingkungan klan suaminya dan dengan demikian menjadi anggota baru dari klan suaminya dengan diberi hak dan kewajiban penuh dalam lingkungan keluarga suaminya). namun susunan rakyat, dusun dan daerah tersebut tetap dalam kesatuan wilayahnya (keadaan serupa juga terdapat di daerah Enggano, Seram dan Flores). Sementara di daerah pesisir, terbentuk dusun-dusun campuran terdiri dari kerabat-kerabat berbagai klan yang mengembara dari pedalaman, serta dari orang-orang asing yang datang dari seberang laut. (Mr. B. Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakrata, 1981, hlm 34-45)
Suku bangsa yang merupakan cikal bakal penduduk asli Pulau Buru adalah suku bangsa Alifuru. Suku bangsa ini merupakan hasil percampuran ras Kaukosoid, Mongoloid dan Papua. Mereka menurunkan keturunan anak-anak suku Alune (berkulit putih) dan suku Waemale (berkulit gelap). Suku Alune diduga berasal dari utara (sekarang Provinsi Sulawesi Utara) yang masuk ke Halmahera dan menyebar ke berbagai daerah di Kepulauan Maluku. Sementara suku Waemale diduga berasal dari timur masuk ke Pulau Seram dan menyebar ke wilayah-wilayah sekitar Pulau Ambon, Kepulauan Lease (Pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut), Pulau Manipa, Pulau Ambalau, dan Pulau Buru. (Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1978, hlm 10)
Proses penyebaran suku bangsa Alifuru ke sekitar Pulau Seram seperti Pulau Ambon, Kepulauan Lease, Manipa, Ambalau dan Buru berlangsung jauh sebelum tahun 1475. Pada tahun itu penyebaran mereka semakin deras seiring dengan tekanan dari penguasa Ternate dan pertikaian diantara mereka sendiri dalam bentuk perang suku. Mereka yang tinggal di Pulau Buru menetap di sekitar pesisir pantai Namlea, Leksula, Namrul, dan Kayeli. Pada pertengahan abad ke-17, kekuasaan Kesultanan Ternate sudah sampai di daerah Maluku bagian tengah yang meliputi Jasirah Hoamoal di Pulau Seram, Kepulauan Lease, Pulau Manipa, Pulau Kelang, Pulau Boano, Pulau Ambalau dan Pulau Buru. Sultan Ternate mempercayakan pengawasan daerah-daerah tersebut pada seorang gimalaha yang berkedudukan di Jasirah Hoamoal di Pulau Seram. Jasirah ini sendiri sejak pertengahan abad ke-16 merupakan penghasil tanaman cengkeh utama di Maluku bagian tengah. Ketika “pendatang” baru berdatangan masuk, mereka terdesak ke pedalaman pulau itu. Mereka kemudian menetap secara nomaden di lembah dan lereng-lereng pegunungan, tetapi lebih banyak yang memilih di pinggir-pinggir sungai. Suku bangsa Alifuru yang menempati Pulau Buru mengambil adat istiadat serta kepercayaan tempat asal mereka yakni Pulau Seram. Karena itu mereka menyebut Pulau Seram sebagai Nusa Ina (pulau ibu). (F.L. Cooley, Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah 1475-1675, dalam Paramita R, Abdulrahman, R.Z. Leirissa, C.P.F. Luhulima (eds), Bunga Rampai Sedjarah Maluku, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, Jakarta, 1973, hlm 118-119)
Suku bangsa Alifuru di Pulau Buru ini kemudian membentuk masyarakat genealogis menurut garis keturunan Ayah (patrinial). Masyarakat ini terus berkembang mencapai kesatuan politik (polity) lebih nyata yang berpuncak pada terbentuknya suatu negeri. Proses pembentukan negeri di Pulau Buru dimulai dari mata rumah yang berkumpul menjadi rumah tau dan membentuk soa. Sejumlah soa kemudian sepakat untuk membentuk negeri.
Mata rumah merupakan keluarga batih beranggotakan pasangan suami istri (orang tua) beserta anak-anak. Perkawinan maupun kelahiran merupakan peristiwa sangat penting dalam memperluas mata rumah. Sementara peristiwa kematian diantara keluarga batih, atau suami istri yang tidak mempunyai keturunan merupakan salah satu faktor yang mengarangi perluasan mata rumah. Beberapa mata rumah menggabungkan diri dalam teritorial tertentu yang disebut rumah tau. Setiap rumah tau penduduk asli pedalaman lembah Waeapo sampai dengan awal 1970-an rata-rata terdiri dari 4-5 mata rumah. Beberapa rumah tau yang mempunyai hubungan genealogis-teritorial bergabung menjadi soa. Soa yang tergabung dalam negeri Kayeli, khususnya yang tersebar di pedalaman lembah Waeapo, biasanya terdiri atas 10-20 rumah. Mereka masih mempunyai pertalian darah erat atau hubungan kerabat. (I.G. Krisnadi, Tahanan Politik Pulau Buru, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001, hlm 20-21)
Masing-masing soa dipimpin oleh seorang Kepala Soa. Jabatan itu diperoleh melalui pemilihan diantara para anggota soa berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan seperti pengalaman, keberanian, dan kepandaian. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Soa dibantu oleh seorang kepala adat (mauweng). Sebagaimana dengan pemilihan kepala soa, mauweng juga dipilih melalui pemilihan diantara para warga soa berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan terutama penguasaan adat istiadat, kebijaksanaan dan kepandaian berbicara. Kepala adat lebih banyak berperan sebagai imam, yang memimpin upacara-upacara adat dan sebagai dukun yang bertugas menyembuhkan warga soa. Jika kepala soa atau kepala adat tidak memenuhi atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan secara adat, diadakan pemilihan baru diantara warga soa. Mereka yang berhak ikut dalam pemilihan hanya laki-laki dewasa.
Setelah Soa yang berdekatan kemudian bergabung menjadi negeri. Kepala Soa yang terkuat dan terpandai dipilih untuk memimpin sebuah negeri. Dua istilah jabatan bagi kepala soa yang memimpin negeri yaitu “Raja” dan “Patih”. Negeri kayeli, Tifu dan Namlea masing-masing dipimpin seorang Raja. Sementara negeri Lisella, dan Liliali, masing-masing dikelola oleh seorang kepala soa bergelar Patih (adipati). (I.G. Krisnadi, Op Cit, hlm 21)
Para Patih maupun raja di berbagai negeri di Pulau Buru dikenal pula sebagai orangkaya. Mereka berperan penting dalam perdagangan cengkeh pada abad ke-17. Mereka mengumpulkan hasil panen cengkeh penduduk negeri untuk diserahkan sebagian kepada Sangaji-penguasa Pulau Buru yang berkedudukan di Negeri Lumaite, pesisir pantai Teluk Kayeli-sebagai upeti dan sebagian lagi dijual di kota pelabuhan setempat. Hanya orangkaya saja yang berhak menjual cengkeh, penduduk umumnya dilarang menjual cengkeh. Sebagai petinggi adat mereka juga berperan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapai oleh masyarakatnya. (G.E. Rumphius dalam Z.J. Manusama (ed), Ambonsche Landbeschrijving, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 5. lihat juga R.Z. Leirissa, Tinjauan Atas Politik Perdagangan VOC di Maluku, dalam E.P.F. Luhulima (ed), Bunga Rampai Sejarah Maluku, Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Jakarta, 1971, hlm 134,148,149)
Selain Hinolong, dan kepala Soa, dikenal juga perangkat pemerintahan adat yang lain yaitu Marinyo dan Kewang. Marinyo bertugas menyampaikan informasi dari Raja kepada seluruh masyarakat melalui Hinolong dan Kaksoding. Apabila Raja akan berkunjung di daerah petuanannya maka informasi ini akan disampaikan kepada mereka dan selanjutnya dilakukan berbagai acara persiapan penyambutan. Raja akan disambut disuatu tempat khusus yang terletak di Metar untuk menyaksikan tarian-tarian penyambutan, di dataran rendah Waepu disebut Wabloy selanjutnya Raja menuju balai pertemuan yang disebut dengan nama Titafena (Tita artinya perintah Raja, Fena artinya kampung).
Kewang berfungsi sebagai pejabat yang memegang kekuasaan sebagai wakil Raja untuk menjaga sumber daya alam. Kewang sangat berperan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam beserta segala sesuatu yang berada didalamnya. Kewanglah yang menentukan suatu kawasan adat boleh dibuka oleh setiap warga adat untuk dipakai sebagai lahan pertanian atau kebun. Juga berperan dalam menentukan sasi adat terhadap setiap kebun pertanian yang dikelola oleh warganya. Selain itu ia juga dapat memberikan pertimbangan kepada Raja jika seseorang warga yang telah mengolah lahan adat dengan ditanami tanaman umur panjang seperti pohon kelapa maka lahan tersebut dapat dialihkan hak dari tanah adat menjadi milik pribadi warga tersebut melalui pelepasan hak dari Raja. Namun hal ini hanya berlaku sepanjang tanah tersebut tetap dalam pengelolaan oleh yang bersangkutan. Namun jika tanah tersebut sudah tidak diolah (dibiarkan terlantar) maka status kepemilikan tanah tersebut kembali menjadi milik bersama masyarkat hukum adat petuanan.
2. PROFIL MASYARAKAT ADAT (RECHTSGEMEENSCHAP) LILIALI
Kabupaten Buru selain memiliki wilayah administrasi pemerintahan yang secara administrasi terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 106 (seratus enam) desa dan Dusun sebanyak 120 (seratus duapuluh) dusun. Selain itu juga memiliki sistem pemerintahan adat yang terdiri atas 8 (delapan) rechtsgemeenschap yang sampai saat ini masih eksis di dalam menangani masalah adat dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sebagai aset kekayaan budaya daerah. (Peraturan Bupati Buru Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Tahun 2007-2012, Pemerintah Kabupaten Buru Mei 2007, hlm 26)
Pada beberapa versi (perlu diteliti kebenaannya lebih lanjut) bahwa diceriterakan Pulau Buru, awalnya terbagi atas dua bagian besar wilayah persekutuan hukum adat, dengan hak ulayat terhadap lingkungan wilayah adatnya yang oleh bangsa Belanda disebut dengan nama Rechtsgemeenschap. Kedua wilayah persekutuan hukum adat tersebut adalah Rechtsgemeenschap Kayeli dan Rechtsgemeenschap Masarete.
Untuk Rechtsgemeenschap Kayeli terbagi atas empat bagian petuanan yaitu Petuanan Kayeli sebagai pusat pemerintahan adat yang dikepalai oleh seorang Raja, Petuanan Liliali dipimpin oleh seorang yang bergelar Pati sebagai wakil Raja Kayeli, petuanan Tagalisa dipimpin oleh seorang bergelar Pati sebagai wakil Raja Kayeli, petuanan Lisela dipimpin oleh seorang bergelar Pati sebagai wakil Raja Kayeli.
Sedangkan untuk Rechtsgemeenschap Masarete pada awalnya sesuai peta adat berangka tahun 1886, terbagi atas delapan wilayah petuanan yaitu petuanan Masarete, petuanan Hukumina, petuanan Palumata, petuanan Tomahu, petuanan Fogi, petuanan Gibrihi, petuanan Waesama dan petuanan Lumaete. Dalam versi yang lain diceriterkan bahwa dari dulu petuanan-petuanan tersebut diatas juga disebut sebagai Rechtsgemeenchap dan masing-masing Rechtsgemeenchap dipimpin oleh Raja. Pada masa penjajahan Belanda, seiring dengan perkembangan pengaruh Belanda dengan alasan pertimbangan keamanan maka pada tahun 1926, petuanan Hukumina, petuanan Palumata, petuanan Tomahu, petuanan Gibrihi dan petuanan Lumaete dihilangkan atau ditiadakan dan seluruh masyarakat adat yang tergabung dalam kelompok masyarakat hukum adat petuanan Masarete oleh pihak Belanda di Pulau Buru diperintahkan untuk berkumpul dan membangun wilayah adat baru di kota Kayeli. Oleh karena perintah tersebut maka seluruh masyarakat hukum adat petuanan Masarete dengan semua petuanan adatnya datang dan berkumpul di kota Kayeli sebagai pusat kota adat di Pulau Buru dengan membangun mesjidnya masing-masing sebagai tanda petuanannya sehingga bertambah satu petuanan baru yaitu petuanan Masarete II. Pertimbangan Belanda saat itu adalah dengan maksud untuk mempermudah kontrol dan pengawasan Belanda atas masyarakat di Pulau Buru. Hal ini dilakukan dengan tujuan strategis yaitu mencegah meluasnya gerakan anti Belanda sebagai imbas dari perang Hatuhaha yang sedang terjadi ketika itu di pulau Ambon dan Seram dengan demikian diharapkan tidak meluas sampai ke Pulau Buru. Peninggalan yang dapat terlihat sampai saat ini di kota kayeli adalah berupa benteng pertahanan Belanda. Kemudian pada beberapa tahun setelah itu para penguasa adat merasa tidak aman untuk berkumpul semuanya di Kayeli maka pada tahun 1936, seluruh masyarakat petuanan kembali ke wilayah adatnya masing-masing sehingga dengan sendirinya petuanan Masarete II dihilangkan dan sebagai gantinya dimunculkan suatu petuanan baru yang disebut dengan petuanan Ambalau.
Kedua petuanan tersebut dipimpin oleh seorang Raja yang menjalankan fungsi kekuasaan dalam struktur pemerintahan adat (eksekutif), disamping itu juga menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif sebagai hakim adat yang tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Jika perkara itu masih dalam batas ringan atau bersifat sederhana maka cukup diputuskan oleh para Kaksoding (wakil Raja) dengan dibantu oleh kepala Soa bagi masyarakat adat yang berdiam di dataran tinggi Waeapu. Sedangkan khusus oleh Hinolong (wakil Raja) beserta kepala Soanya adalah bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dataran rendah Waeapu. Semua proses ini dilakukan dalam suatu sidang adat yang didahului dengan prosesi ritual adat dan diakhiri dengan keputusan dalam bentuk sumpah adat.
Menurut versi Raja Liliali bahwa selain rechtsgemeenschap Kayeli, sejak dahulu juga sudah ada Rechtsgemeenschap Liliali. Sebagai salah satu dari 8 (delapan) rechtsgemeenschap di Pulau Buru. Rechtsgemeenschap Liliali memiliki wilayah petuanan tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Namlea dan Kecamatan Wablau, meliputi 16 desa dan 13 dusun. Secara geografis semuanya terletak di Buru Utara Timur. Desa-desa dan dusun dimaksud adalah sebagai berikut:
Di Kecamatan Namlea adalah:
(1). Desa Namlea dengan 8 (delapan) dusun yaitu Nametek, Rete, Mena, Bara, Sehe, Batu Boy, Jiku besar, dan Tatanggo.(2). Desa Lala.(3). Desa Karang Jaya.(4). Desa Ubung. (5). Desa Jikumera.(6). Desa Waimiting.(7). Desa Sawa.(8). Desa Waeperang.(9). Desa Siahoni.(10). Desa Jamilu.(11). Desa Sanleko dengan 1 dusunnya yaitu Marloso.
Di Kecamatan Wablau adalah:
(1). Desa Wablau.(2) Desa Waeura.(3) Desa Samalagi.(4) Desa Lamahang dengan 3 dusunnya yaitu Rata Gelombang, Lokasi, dan Silmai.(5) Desa Namsina dengan 1 dusun yaitu Waelessi
Pengertian masyarakat tentang arti Petuanan selalu dikaitkan dengan kekuasaan Raja dan selalu identik dengan pengertian rechtsgemeenschap. Menurut masyarakat di Desa Jikumerasa Kecamatan Namlea (termasuk dalam petuanan Liliali) diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang arti petuanan adalah Kekuasaan Raja dimana Raja tersebut berkuasa di daerah kekusaannya artinya ia memiliki tanah ulayat di situ dan mempunyai kepala soa. Istilah lainnya yang mengikuti kata petuanan ini, biasa dengan sebutan negeri jadi petuanan negeri, sehingga tidak pernah ada istilah petuanan desa.
Ada juga yang mengartikan petuanan sebagai kekuasaan Raja atas suatu rechtsgemeenschap yang menguasai beberapa desa.
Kepala desa Ubung mengartikan petuanan sebagai suatu wilayah masyarakat adat yang dipimpin oleh seorang Raja, diatur oleh adat dan dibagi menurut rechtgamanshaap. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian petuanan menurut Raja mereka (Raja Liliali) yaitu bahwa Petuanan dapat diartikan sama dengan rechtgemenshaap. Rechtgemenshaap Raja Lilially terdiri atas 4 soa yaitu : Soa Bessy, Soa Hatalessy, Soa Tinggapy dan Soa Turaha.
Menyangkut dengan status kepemilikan tanah di rechtsgemeenschap Liliali, disampaikan oleh salah satu warga desa Jikumerasa, bahwa ada wilayah tanah yang dikuasai oleh penduduk secara perseorangan, di samping itu juga ada tanah-tanah ulayat yang berada dibawah petuanan Raja, juga terdapat tanah-tanah masyarakat yang dimiliki secara bersama/kolektif oleh suatu komunitas soa tertentu yang diperoleh dengan cara pemberian dari Raja maupun pemberian dari Belanda. Tanah-tanah inilah yang dikuasai oleh penduduk setempat
Masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan “petuanan” atau “wilayah yang dikuasainya” hubungan ini berlangsung terus menerus, dijaga dan dipertahankan.
Kondisi sosial dan budaya masyarakat adat Rechtsgemeenschap Liliali, sangat dipengaruhi oleh kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari indikator kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial melalui kontribusi berbagai bidang. Dibidang kependudukan, kepadatan penduduk tergolong rendah dan tidak merata. Di Desa Jikumarasa sebagai pusat pemerintahan adat, jumlah penduduknya hanya 2. 478 jiwa, di Desa Lala 1.253 jiwa dan di Desa Ubung 1.805 jiwa
Konsentrasi penyebaran penduduk lebih banyak bermukim di wilayah pesisir, dan bersifat heterogen karena sebagian besar masyarakatnya didominasi oleh warga pendatang. Di Desa Lala, mayoritas masyarakatnya adalah pendatang, di Desa Ubung juga demikian yaitu 85 % berasal dari Sanana Maluku utara, 0.4 % berasal dari Flores, 0.2 % berasal dari Jawa dan 0.3 % adalah masyarakat suku Boton. Di Desa Jikumerasa, penduduk asli hanya 40 % sementara warga pendatang mencapai 60 %, mereka berasal dari Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan lain-lain. Mayoritas umumnya beragama Islam dengan mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan nelayan.
Di bidang budaya dan adat istiadat menurut Raja Liliali bahwa meskipun derasnya penetrasi budaya luar yang masuk, yang dibawa oleh warga pendatang maupun karena tingkat mobilitas penduduk asli yang tinggi dengan warga pendatang dalam berinteraksi dan berakulturasi ternyata tidak mengurangi penghayatan masyarakat akan jati dirinya sebagi masyarakat adat Liliali
Hal senada juga disampaikan oleh bebarapa kepala desa di rechtsgemeenschap Liliali bahwa masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan dari leluhurnya dan kita bersama mempunyai tanggung jawab untuk supaya bagaimana adat ini dapat terus dipertahankan. Adat istiadat di sini masih relevan dengan kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat adat, contohnya bila ada sengketa mengenai tanah, kami selalu menemui Raja untuk minta diselesaikan dan memutuskannya.
Demikian pula pendapat dari Bagian Hukum Pemda Buru. Bahwa masyarakat adat di Buru masih takut dengan adanya pamali. (Pamali adalah pantangan atau aturan adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakat adat. Pamali dipercaya sebagai warisan nilai-nilai luhur yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam soa dan negeri karena itu pamali ditaati dijunjung tinggi sekaligus ditakuti jika dilanggar karena mereka akan menerima sanksi yang setimpal dengan ketentuan adat).
- EKSISTENSI OTORITAS ADAT DALAM SISTEM PERADILAN INFORMAL PADA RECHTSGEMEENSCHAP LILIALI DI KABUPATEN BURU (RECHTSGEMEENSCHAP JUDICIAL AUTONOMY STUDY)
- TUGAS DAN KEDUDUKAN RAJA SEBAGAI PEMANGKU OTORITAS DALAM PERADILAN ADAT
Sosok Raja sampai saat ini masih eksis didalam menangani masalah adat dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sebagai aset kekayaan budaya daerah. (Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005-2025, hlm 41)
Tugas dan kedudukan Raja di dalam masyarakat adat Liliali sangat penting dan strategis karena berperan di hampir semua perikehidupan masyarakatnya, mulai dari tradisi menyambut kelahiran seorang anggota baru dalam masyarakat adatnya sampai dengan penyelenggaraan prosesi ritual, dari kematian salah satu anggota warga masyarakat adatnya. Tugas seorang Raja secara garis besarnya juru tulis Raja (sekertaris Raja) mencakup:
(1). Menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan adat
(2). Mewakili kepentingan masyarakat adat secara keluar
(3) Mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah negeri/ulayat, tanah soa/tua-tua adat dan tanah perseorangan yang bersumber pada hak ulayat.
(4). Memelihara dan menjaga aturan-aturan hukum adat agar ditaati sebagai tata tertib sosial dan hukum di masyarakat dalam rangka upaya preventif.
(5). Menyelenggarakan dan memimpin peradilan adat bila terdapat sengketa dimasyarakat untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan akibat terganggunya tata tertib sosial dan tata tertib hukum (upaya bersifat represif)
Kedudukan Raja Liliali adalah sebagai pemimpin tertinggi Saniri Besar persekutuan hukum adat yang secara hirarki dimulai dari Raja (Pimpinan Saniri Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali), kemudian anggota badan saniri besar terdiri atas kepala-kepala soa, para pemuka adat dan pemuka agama, kewang dan marinyo.
Saniri Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali mempunyai kedudukan dan tugas administrasi yang dijalankan oleh Raja dalam fungsi legislatif maupun yudikatif, seperti membuat peraturan dan menentukan kebijaksanaan pemerintahan serta membuat keputusan atas suatu sengketa dan ditetapkan melalui paripurna Saniri Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali. Namun adakalanya untuk kasus-kasus sengketa tertentu, langsung diputuskan oleh raja sendiri tanpa bantuan anggota saniri. Hal itu biasanya terjadi bilamana raja merasa bahwa dapat meyelesaikannya sendiri karena mengetahui secara betul pokok persoalan yang disengketakan. Pengetahuan raja yang sangat mendalam tentang tanah-tanah yang dimiliki masyarakatnya disebabkan karena raja memiliki buku tentang riwayat tanah-tanah yang terletak dalam rechtsgemeenschapnya.
2. TIPOLOGI KASUS YANG UMUMNYA DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN INFORMAL
Pada tingkat lokal umumnya masyarakat mempunyai berbagai pilihan penyelesaian atas kasus-kasus yang terjadi, diantaranya melalui sistem peradilan formal. Namun mereka cenderung memilih mekanisme sistem peradilan informal. (Sistim peradilan “informal” artinya semua penyelesaian sengketa yang terjadi di luar sistem peradilan formal. yaitu pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Penyelesaian sengketa “informal” tidak terbatas pada mekanisme adat), karena mekanisme ini lebih murah, lebih cepat, fleksibel dan lebih dapat diakses dibanding sistem formal. Kasus-kasus yang umumnya diselesaikan melalui peradilan informal adalah dengan diskripsi tipologi kasus sebagai berikut:
1. Kriminal ringan, perkelahian, pencurian hasil kebun, perusakan harta benda, kerusuhan. Isu Sengketa berkaitan dengan adanya faktor dendam pribadi, tingkat pendapatan yang rendah dan termakan provokasi sebagai imbas konflik kerusuhan Maluku
2. Penyakit sosial (Judi,dan mabuk-mabukan) umumnya hanya dianggap sebagai pengisi waktu luang dan refreshing setelah lelah bekerja seharian di kebun namun konflik biasanya terjadi karena timbulnya kesalahfahaman.
3. Kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan. Faktor ketidakcocokan dan pertengkaran sering menjadi penyebab konflik. konflik ini bukan dianggap sebagai tindak pidana bahkan bukan merupakan sesuatu hal yang serius. Raja dianggap sebagai sosok orang tua yang pantas dimintai nasehatnya. Sifat patrilinial masyarakat adat menyebabkan Perempuan sering menerima solusi apa adanya tanpa diikutsertakan secara langsung dalam proses penyelesaian.
4. Hamil di luar nikah dan perzinahan/asusila. Berawal dari pihak pelaku (laki-laki) yang ingin lari dari tanggung jawab. Meskipun kasus ini diakui jarang terjadi namun biasanya penyelesaiannya hanya melibatkan kedua keluarga yang berselisih dan raja biasanya meminta bantuan pemuka agama untuk memberikan pencerahan. Perempuan selalu menjadi pihak yang dipersalahkan dan menjadi obyek untuk harus menerima solusi apapun yang disepakati.
5. Sengketa tanah. Jenis konflik sangat sering terjadi yaitu berupa sengketa batas tanah, hak atas tanah warisan, hak kepemilikan tanah antara pendatang dengan penduduk setempat, pemerintah dan investor swasta.
6. Konflik sumber daya alam. Misalnya perebutan bahan galian C (pasir, batu dan kerikil) di sungai yang merupakan daerah perbatasan antar suatu soa atau desa. Hal ini adalah karena imbas dari adanya proyek pembagunan jalan dan jembatan. Dan perebutan lahan pohon kayu putih untuk penyulingan minyak kayu putih antar masyarakat dan pemerintah.
- SISTEM PERADILAN INFORMAL PADA RECHTSGEMEENSCHAP LILIALI
Aktor penyelesaian sengketa di peradilan informal pada tingkat lokal menerapkan aturan hukum yang didasarkan pada tradisi lisan secara turun temurun yang merupakan kolaborasi antara gagasan perdamain, keadilan dan keharmonisan serta akal sehat. Aturan tersebut ada yang sudah menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku dalam komunitas masyarakat adat yang hidup dan dihormati sebagai bentuk kearifan lokal setempat.
Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara sederhana, cepat dan tanpa ada biaya yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara. Para pihak yang bersengketa pada dasarnya mempunyai pilihan yang fleksibel tentang aktor penyelesaian sengketa dan biasanya mereka memilih mekanisme pada tingkat yang paling rendah terlebih dahulu karena memungkinkan dapat dengan mudah diakses oleh kedua belah pihak seperti kepala dusun, kepala soa, dan kepala desa.
Terhadap kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka yang berada pada tingkat bawah maka biasanya diteruskan ke Raja dan Saniri Besar untuk diputuskan. Begitupun bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan ditingkat bawah dapat meneruskan perkara tersebut guna diselesaikan lebih lanjut melalui putusan Raja dan Saniri Besar.
Para pihak juga diberikan kebebasan untuk dengan inisiatifnya sendiri, membawa perkara tersebut langsung ke raja dan Saniri Besar tanpa harus perlu lebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana tersebut diatas (tidak dikenal adanya banding).
Menurut mereka dalam proses berperkara tidak dikenal adanya hukum acara yang baku dan semua prosesnya tidak harus dalam bentuk tertulis. Semua proses berjalan secara lisan terkecuali ada hal-hal tertentu yang dianggap penting untuk dicatat. Semua pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara, mengajukan bukti-bukti dan saksi. Dalam hal apabila para pihak tidak memiliki bukti-bukti yang dapat diajukan maka prosedur yang ditempuh adalah mengucapkan sumpah yang dipimpin oleh imam mesjid (pemuka agama). Cara ini diakui dan dirasakan cukup ampuh dan efektif dalam menyelesaikan suatu perkara karena masyarakat merasa takut akan akibatnya dan meyakini bahwa sanksi Tuhan lebih berat dari sanksi apapun.
Khusus menyangkut obyek sengketa tanah dan sumber daya alam, apabila dianggap perlu maka raja biasanya akan memerintahkan kepala-kepala soanya untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan obyek sengketa, guna mendapatkan kejelasan dan kebenaran yang sesungguhnya atas obyek sengketa tersebut, proses dimaksud sama dengan sidang komisi (sidang pemeriksaan ditempat obyek sengketa) seperti yang dikenal dalam sistem peradilan formal. Hasilnya kemudian akan dilaporkan kepada raja dan menjadi bahan pertimbangan bagi raja dan musyawarah Saniri Besar dalam mengambil keputusan. Terkadang proses ini juga dilampaui apabila Raja dan para Kepala Soa telah hafal betul dan mengetahui persis letak obyek sengketa yang dipersoalkan sehingga merasa prosedur itu tidak perlu untuk dilakukan.
Hasil akhir dari proses tersebut berupa keputusan raja dan atau Saniri Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali. Dalam perkembangannya sekarang, sebelum keputusan ini dibacakan terlebih dahulu para pihak yang bersengketa diminta untuk membuat pernyataan yang berisikan bahwa mereka yang berperkara bersedia dan siap menerima apapun keputusan yang nantinya diambil. Di masa pemerintahan raja terdahulu pernyataan semacam ini belum pernah ada.
Umumnya masyarakat menerima dengan ikhlas apapun keputusan yang dibuat, namun demikian tidak dipungkiri juga oleh raja bahwa ada satu kasus dimana salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang dibuat, kemudian melanjutkan perkaranya ke peradilan formal (Pengadilan Negeri Ambon).
Keputusan biasanya dihasilkan melalui musyawarah dan jika dikehendaki oleh para pihak dapat dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan Saniri Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali yang ditanda tangani oleh Raja berserta alat kelengkapan Saniri Besar, namun umumnya disampaikan secara lisan. Keputusan yang dibuat tersebut sering kemudian menjadi aturan hukum baru yang berkekuatan hukum tetap pada masyarakat adat dan turut memperkaya khasanah hukum adat mereka
Upaya eksekusi tanah obyek sengketa hampir tidak pernah dilakukan karena semua pihak cukup taat terhadap keputusan yang telah dibuat. Eksekusi berjalan secara alami tanpa harus ada upaya paksa dari Raja maupun Saniri Besar karena pihak yang kalah dengan sendirinya akan mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa dan secara otomatis langsung diambil alih dan dikuasai oleh pihak yang dimenangkan.
Dalam kasus konflik batas tanah antar rechtsgemeenschap yang bertetangga dalam ingatan salah satu sesepuh masyarakat Desa Jikumerasa bahwa pernah juga terjadi sengketa seperti itu namun dapat diselesaikan diantara raja-raja mereka, beliau mengatakan sebagai berikut, Dahulu sekali saya ingat kalau ada persoalan seperti ini diselesaikan langsung oleh raja-raja dan persoalnnya langsung selesai saat itu juga, mungkin karena mereka masih hubungan keluarga, sebab mereka saling mengawini antar anak-anak raja.
Pada kasus-kasus tertentu (umumnya kasus Kriminal ringan, perkelahian, pencurian hasil kebun, perusakan harta benda, kerusuhan, pemberantasan penyakit sosial, kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga, kasus asusila dan konflik sumber daya alam), biasanya raja dan Saniri Besar mengambil peran sebagai mediator.
Hasil mediasi cukup beragam disesuaikan dengan kasus dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku. Umumnya sanksi yang diberikan juga tergolong ringan seperti untuk kasus kriminal ringan, perkelahian, perusakan harta benda, dan kerusuhan, diharuskan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dan kemudian mendamaikan dengan cara pelaku diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa. Khusus dalam kasus pencurian hasil kebun, biasanya dikenakan denda adat berupa kuali(pengorengan) tembaga besar sebanyak 10 buah, kain berang (kain berwarna merah darah) dan lenso kepala (kain ikat kepala). Kalau yang dicuri itu adalah daun dari pohon kayu putih (bahan baku penyulingan untuk pembuatan minyak kayu putih) maka pelakunya diharuskan membayar kerugian kepada korban pencurian dalam bentuk minyak kayu putih (hasil penyulingan) sebanyak yang ditentukan oleh Raja.
Terhadap kasus penyakit sosial seperi judi dan mabuk-mabukan, upaya yang ditempuh berupa pemberian nasehat dengan harapan agar para pelaku menyadari perbuatannya. Dalam situasi tertentu seringkali juga raja menerapkan hukuman fisik yang sifatnya sekedar sebagai sock terapi.
Dalam menyelesaikan kasus seperti kekarasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus-kasus asusila lainnya. Raja memposisikan diri sebagi orang tua. Upaya mediasi lebih banyak ditempuh Raja untuk mencari solusi terbaik, guna tetap menjaga keharmonisan dan agar dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, meskipun terkadang kesepakatan yang dibangun seringkali dirasa kurang adil bagi pihak perempuan selaku korban karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Untuk penyelesaian konflik perebutan sumber daya alam, penyelesaiannya yang ditempuh, juga menggunakan cara-cara mediasi. Raja selalu menempatkan diri pada posisi sebagai hakim yang netral, seperti contoh kasus yang pernah terjadi berikut ini:
Masalahnya berawal dari Perusahaan Kontraktor yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan, mereka hendak membeli batu, pasir dan kerikil (bahan galian golongan C) dari masyarakat. Bahan material tersebut diambil oleh masyarakat dari dalam sungai. Warga Desa Namsina mengatakan bahwa sungai itu adalah milik Desa Namsina namun diklaim oleh warga dari Desa Samalagi. Konflik tersebut berkembang menjadi konflik fisik antar desa dan akhirnya persoalan tersebut dibawa ke Raja Liliali untuk diputuskan. Raja kemudian memutuskan bahwa sungai dan semua isinya adalah anugerah Tuhan untuk kita semua, olehnya itu hendaknya dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemaslahatan semua orang. Jadi jangan diperebutkan. Keputusan Raja bahwa sungai itu dibagi dua, masing-masing mengambil batu, pasir dan kerikil di daerah sungai yang terdekat dengan desa masing-masing. Dan dikelola secara bersama. Kalau tidak, maka sungai itu akan kelola langsung oleh Raja dan hasilnya akan gunakan untuk kepentingan umat dan pembangunan mesjid di rechtsgemeenschap Liliali. Keputuan Raja diterima baik oleh kedua masyarakat desa yang bertikai dan mereka kembali berdamai serta bekerja sama untuk mengelola sungai secara bergotong royong (warga Desa Namsina maupun Desa Samalagi adalah warga pendatang. Penduduk Desa Namsina berasal dari Hatawano, sementara penduduk Desa Samalagi dari suku Buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara). Keputusan Raja dianggap sangat adil karena kedua pihak yang bersengketa merasa tidak ada yang dikalahkan atau dirugikan. Meraka cukup menyadari bahwa Raja bisa saja melakukan intervensi karena mereka bukan penduduk asli. Lagipula tanah-tanah yang mereka tempati adalah hak ulayat dari petuanan Liliali.
Selain itu, masyarakat juga menaruh kepercayaan yang besar terhadap otoritas adat ketika harus berhadapan dengan kepentingan pemerintah dalam konflik vertikal misalnya pada kasus lahan kebun kayu putih mereka yang diambil alih oleh pemerintah daerah tanpa alasan yang jelas. Menurut penuturan Raja Liliai, bahwa kasus 123 buah dusun kayu putih milik petuanan Lilially bermula sejak tahun 1955. Ketika itu Pemda datang ke raja terdahulu. Mereka meminta kontribusi dari raja untuk dapat membantu menghidupi keuangan pemerintah daerah Maluku Tengah (sebelum pemekaran Kabupaten Buru waktu itu masih termasuk dalam daerah administratif Kabupaten Maluku Tengah), dan raja menyetujui untuk memberikan 123 buah dusun kebun minyak kayu putih untuk dikelola oleh Pemda selama 4 s.d. 5 tahun, setelah lewat waktu tersebut maka Pemda harus mengembalikan kepada raja guna selanjutnya raja akan meyerahkan kembali kepada masyarakat adatnya. Ternyata, kenyataannya sampai sekarang dusun tersebut tidak pernah dikembalikan. Upaya hukum melalui pengadilanpun pernah ditempuh tetapi sampai saat ini mengambang tanpa hasil yang jelas. Akhirnya Raja atas nama masyarakat persekutuan hukum adat Liliali menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat membantunya menyelesaikan persoalan tersebut. Walapun Komisi telah mengeluarkan Rekomendasi hasil pemantauannya, ternyata hal itu tidak memberikan pengaruh karena sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Buru belum mau memberikan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat Liliali
4. VOLUME PERKARA DAN TINGKAT OTORITAS ADAT DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA
Untuk mengetahui secara pasti volume perkara yang ditangani oleh Raja sendiri maupun bersama-sama dengan perangkat Saniri Besar Persekutuan Hukum Adat diakui sangatlah sulit mengingat tidak semua putusan dilakukan secara tertulis (tidak terdokumentasi secara baik), karena sebagian besar perkara diputus secara lisan (walaupun begitu ada juga beberapa perkara yang putusannya dibuat secara tertulis) atas permintaan para pihak yang bersengketa.
Menurut penuturan Raja Liliali bahwa dalam masa pemerintahannya mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2008 jumlah perkara yang telah berhasil diputuskannya kira-kira sudah berjumlah lebih dari 100 buah perkara, karena seingatnya hampir setiap bulan selalu ada saja perkara yang masuk. Kalau dirata-ratakan bisa mencapai 12 sampai 15 perkara per tahun. Jenis kasus yang diselesaikan beragam namun yang paling dominan adalah kasus sengketa tanah.
Keterangan Raja Liliali ini ketika dikonfrontir dengan Kepala Desa Ubung. Kepala Desa tersebut mengakui kebenarannya karena menurutnya selama masa pemerintahannya selaku Kepala Desa Ubung, bahwa sejak dilantik dari bulan Pebruari 2005 sampai dengan sekarang, seingatnya sudah 10 perkara tentang sengketa tanah antar warga maupun antara warga di desanya dengan perusahaan daerah PD. Pradja karya (perusahaan daerah Kabupaten Buru yang mengolah penyulingan minyak kayu putih) yang diselesaikan dan diputuskan oleh Raja, namun putusan Raja tersebut tidak mendapat respon dari perusahan tersebut.
Dengan demikian maka tingkat otoritas adat dalam menangani suatu perkara berada pada tingkat partisipatif yang cukup tinggi apalagi kalau dimasa pemerintahan raja yang terdahulu (Bahaddin Bessy, 1930 s.d. 2002) dikatakan oleh Raja Liliali (Sudirman Bessy, 2002 s.d 2006) bahwa bapaknya itu sering menangani perkara 1 sampai 2 perkara per minggu karena hampir setiap minggu selalu saja ada perkara yang harus beliau selesaikan.
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Waeperang bahwa ia cukup tahu persis bagaimana sibuknya Tete raja ( Raja terdahulu yaitu Bahaddin Bessy) menyelesaian persoalan warga persekutuan masyarakat hukum adatnya. Bisa dapat pastikan bahwa hampir setiap malam rumah Raja itu selalu ramai didatangi warga karena ingin menyaksikan digelarnya persidangan adat. Raja waktu itu meskipun dalam kondisi mengalami gangguan pendengaran karena faktor usianya yang sudah sepuh, namun beliau masih tetap bisa menyelesaikan semua perkara secara baik. Dan permasalahan sengketa tanah adalah yang paling menonjol dibandingkan kasus lainnya. Kebetulan rumah Raja di Desa Waeperang berdekatan dengan rumahnya, sehingga ia tahu betul keadaan pada masa itu.
Tingkat otoritas adat dapat juga dilihat dari parameter aksesibilitas aktor peradilan informal (Raja dan Saniri Besar) yang dipercaya warga dalam menyelesaikan persoalan. Mereka (Raja dan Saniri Besar) seperti dikatakan oleh Kepala Desa Ubung sebagi berikut, bahwa masalah tanah di masyarakat kami sering terjadi umumnya pada saat hendak dilakukan transaksi jual beli tanah. Akar permasalahannya terletak kepada perebutan hak kepemilikan karena semua pihak merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut maka biasanya permasalahan itu kalau tidak bisa saya selesaikan, saya menyarankan untuk diselesaikan di Raja. Kami percaya Raja dapat menyelesaikan kasus ini, karena raja memiliki buku tentang riwayat tanah-tanah yang ada disini sehingga dapat diketahui siapa pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut. Demikianpun pendapat Kepala Desa Jikumerasa, dijelaskan bahwa kalau ada warga desanya yang hendak melakukan transaksi jual beli tanah atau rumah maka mereka selalu pergi ke Raja untuk mengurus surat pelepasan hak atas tanah adat. Dan bilamana ada sengketa atas tanah tersebut maka bisanya Raja terlebih dahulu menyelesaikannya.
Aksesibilitas pelayanan dari aktor peradilan informal ini, ternyata dimanfaatkan bukan hanya oleh masyarakat saja tetapi juga oleh aparat pemerintah daerah khususnya Camat. Karena biasanya apabila ada peralihan hak kepemilikan atas tanah melalui jual beli maka Camat selaku pejabat pembuat akte tanah selalu berkoordinasi dengan raja sebelum terjadi proses jual beli tersebut, Camat selalu meminta rekomendasi terlebih dahulu dari raja dan rekomendasi tersebut sangat berarti dalam menentukan terjadinya atau tidak proses jual beli dimaksud. Walaupun demikian diakui juga bahwa tidak semua Camat melakukan hal serupa.
Tingginya tingkat kepercayaan warga terhadap otoritas adat juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan pelayanan dan kecepatan mereka dalam menyelesaikan suatu perkara. Rata-rata semua responden mengakui bahwa waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelesaikan satu kasus paling cepat 1 hari dan paling lama 2 minggu per kasus. Kemudahan lainnya yang diperoleh adalah berupa prosesnya yang sederhana dan fleksibel serta tidak dikenakan biaya apapun.
IV. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
- Masyarakat persekutuan hukum adat Liliali mempunyai sejumlah pilihan penyelesaian konflik ketika mereka berselisih. Mereka cenderung memilih sistem peradilan informal karena mekanisme ini tanpa biaya, lebih cepat, fleksibel dan lebih mudah diakses dibanding sistem peradilan formal.
- Eksistensi otoritas adat dalam sistem peradilan informal dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat akan kemampuan Raja dan Saniri Besar dalam memutuskan suatu perkara. Aksesibilitas pelayanan yang prima, konsistensi dan kualitas putusan yang diakui cukup memberikan kepuasan bagi semua pihak yang bersengketa, dan kewibawaan serta pengetahuan yang luas dalam memahami pokok perkara merupakan faktor yang memperkuat integritas dan kapabilitas mereka.
- Fleksibilitas peran aktor otoritas adat dalam sisitem peradilan informal yang terkadang bertindak sebagai orang tua, penasehat, mediator dan hakim yang netral adalah kekuatan kunci dalam penyelesaian setiap sengketa.
- Efektifitas kinerja otoritas adat dalam peradilan informal hanya terbatas dalam yurisdiksi wilayah hukum adat atau antar wilayah hukum adat tetapi rentan ketika berhadapan dengan pihak pemerintah atau investor swasta dalam konteks eksternal.
- Keunggulan komparatif yang inheren dari eksistensi otoritas adat dalam sistem peradilan informal pada rechtsgemeenschap Liliali adalah merupakan lebenstraum (sumber-sumber kehidupan baik secara simbolis dan maupun realis) bagi Kabupaten Buru dan bangsa Indonesia umumnya.
B. Saran
1. Untuk menjamin akuntabilitas internal dan eksistensi otoritas adat dalam peradilan informal maka perlu diatur adanya mekanisme banding (check-and-balance), keterwakilan perempuan, serta pengaruh penyeimbang antara kekuasaan Raja dan anggota Saniri Besar, sehingga tidak membahayakan sikap netralitas, mencegah putusan yang diskriminatif, potensi manipulasi dan sanksi yang tidak manusiawi dari para aktor otoritas adat tersebut.
2. Perlunya adanya interaksi yang intensif antara sistem peradilan formal dan informal mengingat batasan antara penyelesaian kasus di peradilan informal dan formal masih sangat kabur mengingat keduanya menggunakan sumber hukum yang berbeda.
3. Perlunya konsolidasi kebijakan pemerintah daerah melalui rencana kerja strategi pembangunan yang lebih apresiatif terhadap akses terhadap hukum dan keadilan bagi masyarakat adat secara jelas, konkrit dan nyata.
4. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Buru seyogyanya perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
– Pengakuan secara tegas kedudukan dan keberadaan masyarakat persekutuan hukum adat Liliali dan lainnya
– Pengakuan terhadap tradisi dalam penyusunan kepengurusan masyarakat persekutuan hukum adat termasuk pengakuan terhadap hukum adat yang berlaku dan hak-hak otoritas adat dalam sistem peradilan informal.
5. Disarankan kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat melanjutkan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas dalam rangka menggali dan memberdayakan hukum adat dan memperkaya khasanah hukum Indonesia dan sumber hukum nasional Indonesia. Penelitian dimaksud sangat urgen untuk dapat menemukan suatu model penyelesaian sengketa alternatif melalui peradilan informal dengan pendekatan otoritas adat (rechtsgemeenschap judicial autonomy model) sebagai bagian dari blue print reformasi peradilan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Bushar Muhammad, 2002, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.
B. Ter Haar Bzn, 1981,Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta
F.L. Cooley, 1973, Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah 1475-1675, dalam Paramita R, Abdulrahman, R.Z. Leirissa, C.P.F. Luhulima (eds), Bunga Rampai Sedjarah Maluku, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, Jakarta.
G.E. Rumphius dalam Z.J. Manusama (ed), 1983, Ambonsche Landbeschrijving, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta,
H. Hilman Hadikusuma, S.H., 1986, Antropologi Hukum Indonesia, Alumni, Bandung
I.G. Krisnadi, 2000, Tahanan Politik Pulau Buru, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta Riyanto B, 2004, Pengaturan Hutan Adat di Indonesia Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.R.Z. Leirissa, 1971, Tinjauan Atas Politik Perdagangan VOC di Maluku, dalam E.P.F. Luhulima (ed), Bunga Rampai Sejarah Maluku, Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Jakarta.
Riyanto B, 2004, Pengaturan Hutan Adat di Indonesia Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
PERATURAN :
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2005 yo Keputusan Bupati Buru Nomor 146-51 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Nomor 146-25 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Buru
Peraturan Bupati Buru Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Tahun 2007-2012, Pemerintah Kabupaten Buru Mei 2007
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005-2025
MAKALAH :
PENGADILAN, MARTABAT HAKIM
Pengadilan, Martabat Hakim dan Tradisi Melayu Islam Dalam Mewujudkan Rasa Keadailan Di Masyarakat, Disampaikan dalam Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Negeri Pelelawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Di Siak Sri Indrapura, 23 Februari 2006
LAPORAN :
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007.
Laporan Perkembangan Situasi Yang Berpengaruh Terhadap Eksistensi Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliali, Disampaikan dalam Acara Silaturrahmi Antara Majelis Adat Latupati Maluku Dengan Sultan Jogyakarta, Oktober 2007