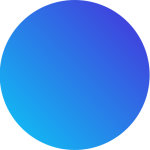INDIKATOR “BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM” SEBAGAI DASAR PEMBATALANPERATURAN DAERAH[1]
Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.[2]
Abstract
Formation regulation must meet the indicator does not contradict the legislation of higher and not contrary to public interest. If both indicators are not met in the establishment of a law, then in the evaluation by the Government, there apabil established law contrary to the legislation of higher and contrary to public interest, the Government may cancel a legal product.
Indicators of general interest in the cancellation law is vague norm, because this indicator is to open a space for the Government to make the interpretation of the meaning of public interest norms. Very complex public interest, public interest is not always to be understood as a national interest, regional interest may also be the public interest because it includes all interests in the communal areas. Interest means the area of interest to all individuals in the region as a whole.
Keywords: Public Interest, The cancellationlaw
A. Pendahuluan
Pelaksanaan sentralisasi kekuasaan pada satu sisi memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pengambilan keputusan, dan di samping itu merupakan alat yang penting untuk menjaga keutuhan suatu negara. Dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu, sistem sentralisasi ini tidak menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di daerah-daerah. Hal ini mengingat negara dengan wilayah yang sedemikian luas, memiliki heterogenitas kepentingan dari masing-masing wilayah yang cukup beragam. Dengan demikian jika sistem sentralisasi ini dijalankan secara kaku, niscaya akan menimbulkan benturan-benturan yang datangnya justru dari heterogenitas kepentingan dari Daerah-daerah tersebut.
Untuk meminimalkan kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan sistem sentralisasi ini, maka salah satu jalan yang dianggap baik untuk ditempuh adalah dengan melakukan penyebaran sentralisasi kekuasaan dalam bentuk pelimpahan atau penyerahan beberapa kekuasaan/kewenangan kepada satu atau beberapa badan tingkatan pemerintahan yang ada di dalam negara itu.Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan Pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.
Penyerahan kekuasaan tersebut tetap harus dalam bingkai negara kesatuan, sebagai sebagai wujud pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUDNRI) Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini berarti bentuk negara kesatuan berkonsekuensi bahwa hanya ada satu pemerintahan nasional yang sah dan satu hukum nasional yang sah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia[3]. Dalam konteks hubungan antara pusat dengan daerah, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah bergeser dari sistem yang sentralistik menjadi sistem yang mengedepankan otonomi dengan berpijak pada prinsip desentralisasi.
Dengan adanya penyerahan kewenangan, Pemerintahan Daerah (selan jutnya disingkat Pemda) berhak menetapkan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan merupakan atribusi kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda). Ini berarti sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi kekuasaan vertikal yang memberikan otonomi kepada daerah, maka Perda merupakan Autonome Satzung sebagaimana diklasifikasi oleh Hans Nawiasky. Hal ini sesuai dengan perkembangan demokrasi di bidang pemerintahan, di mana negara-negara modern banyak memberikan kekuasaan kepada daerah untuk lebih bebas mengatur dirinya.
Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yakni harus membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah. Pemerintah wajib melaksanakan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Selain diberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah Pusat (selanjutnya disingkat Pemerintah) wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Hakekat Desentralisasi dalam Pembentukan Perda
Menurut Rondinelli dan Cheema, decentralization is the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or non-government organizations.[4] Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state.
M.C. Burkens, et.al[5], mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial (decentralisatie territorial) dan desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie). Bij territoriale decentralisatie krijgen de organen van een bepaald openbaar licham in beginsel een algemene bevoegdheid tot wetgeving en bestuur op een deel van het grondgebied van de straat, sedangkan decentralisatie functionale goot het om taakbehartiging met het oog op een bepaald doel. Artinya bahwa desentralisasi tidak dimaksudkan sebagai proses melepaskan diri sama sekali dari pemerintah yang lebih atas, tetapi desentralisasi lebih dikaitkan dengan persoalan pembagian/penyerahan wewenang dari lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah dan yang berada dibawahnya.
Sebagai negara kesatuan, maka desentralisasi merupakan wujud toleransi Pemerintahan Pusat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah dalam hal pemberian wewenang untuk melaksanakan urusan-urusan yang bias menjadi urusan pemerintahan penyelenggara pemerintahan di daerah. Pelimpahan wewenang dalam suatu negara kesatuan, tidaklah berarti bahwa penerima wewenang dapat bertindak tanpa ada pengawasan dari penyelenggara pemerintahan di pusat.
Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk yang ada di setiap daerah.Dengan pelaksanaan desentralisasi, maka kesatuan penyelenggara pemerintahan di daerah lebih memiliki peran dari pada sekedar menjadi pelaksana tugas pemerintahan pusat. Peran yang dimiliki menjadi leluasa karena tersedianya ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap potensi daerah yang dimiliki. Melalui pelimpahan (devolusi) kewenangan ke pemerintah daerah, maka pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru pemerintah yang berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat.
Pelimpahan wewenang dalam desentralisasi ketatanegaraan berakibat beralihnya kewenangan Pemerintah secara tetap. Pemerintahan kehilangan kewenangan yang telah dilimpahkannya dan beralih kepada pihak yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut. Dalam perspektif ketatanegaraan, desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan azas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara.
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan di daerah sebagai kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom. Kebijakan daerah yang dimaksud tersebut secara yuridis normatif tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Sehingga pada prinsipnya Perda merupakan instrumen hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU PPP) terkait dengan pembentukan Peraturan di Daerah yaitu Perda dan Peraturan Kepala Daerah, berarti telah diadakan suatu metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang di daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hal ini berarti pula mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang sinergis serta ideal. Pengertian Perda menurut UU PPP adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
Materimuatan Perda berisi seluruh materimuatan dalam rangkapenyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda merupakan peraturan yang paling dekat untuk mengagregasi nilai–nilaimasyarakat di daerah. Peluang ini terbuka karena Perda dapat memuat nila-nilaiyang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Oleh karena itulah banyak Perda yangmaterimuatannya mengatur tentang pemerintahan terendah yang bercorak lokal.
Perda dalam sistem otonomi daerah memiliki kedudukan yang strategis, karena Perda berkarakter delegated legislation.Menurut Bradley[6], delegated legislation is an inevitable feature of modern government for several reasons
1. Pressure on Parliament Time
If Parliament attempted to enact all legislation itself, the legislative machine would break down, unless there were a radical alteration in the procedure for considering Bills. The granting of legislative power to a department which is administering a public service may obviatethe need for amending Bills. Although many statutory instruments are laid before parliament only a minority of them gives rise to matters which need the consideration of either House and Parliament spends a very small proportion of this time on business connected with them.
2. Technicality of Subject Matter
Legislation on techical topics necessitates prior cunsultation with experts and intersts concerned. The giving of legislative power to minsters facilitates such consultation. Draft Bills are often regarded as confidential documents and their text is not diclosed until they have been presended to parliament and read a first time. No such secretive custom need impede the preparation of delegated legislation. There is also a good reason for keeping out of the statute book highly technical provisions which do not involve questions of principle and which only experts in the field concerned can readly understand.
3. The Need for Flexibility
When a new public service is being established, it is not possible to foresee every administrative difficulty that may arise or to have frequent recourse to Parliament for amending Acts to make adjustments that may be called for after the scheme has begun to operate. Delegated legislation fills those needs. When the community charge, or pol tax, came into operation under the Local Government Finance Acts 1988, as amended in 1989, no fewer than 47 sets of regulations were made in the years 1989-1991. But even such extensive exercise of delegated powers could not prevent the tax from being failure. A power commonly delegated to ministers is the power to make a commoncement order, bringing into operation all of part of a statute. Often there are practical reason why a ‘new act should not come in to effect as soon as the royal assent is given. There is no duty on the ministr to exercise a commencement power, but the minister must not act so as to defeat Parliament expectation that the act will come into operation.
4. State of Emergency
In time of emergency a government may need to take action quickly and inexcess of the normal powers. Many written constitutions include provision in emergency for the suspention of formal quarantees of individual liberty. Although the Crown possesses an ill-defined residue of prerogative power capable of use in time of national danger, the Emergency Power Acts 1920 makes permanenet provision enabling the executive to legislative subject to parliament ant safeguards in the event of certain emergencies. On the return of Northern Ireland to direct rule by the British Government in 1972, wide power to legislative for Northern Ireland was conferred on the Queen in Council. This enable laws to be made for Northern Ireland by order in council, a procedure which does not allow full scope for democratic discussion.
Perda sebagai delegated legislation, muatan materinya harus menjabarkan ketentuan dan isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Indikator menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah kontradiktif, karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda berisi pengaturan yang bersifat umum. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda juga merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi. Yang lebih penting adalah tidak ada jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda bersifat koheren atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya karena peraturan perundang-undangan itu masih dimungkinkan untuk diuji.
Mengenai ciri khas dan karakteristik daerah, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini sangat jamak, karena masing-masing daerah memiliki ciri khas dan karakter tersendiri. Walaupun beberapa daerah dapat dikatakan merupakan daerah kepulauan, misalnya, tetapi ciri dan karakter masing-masing daerah tetap berbeda. Contoh lain misalnya, dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota, terdapat kemajemukan masyarakat di dalamnya. Kemajemukan bahasa, agama, adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya, kemajemukan ini yang turut mempengaruhi perilaku dan ciri khas masing-masing daerah. Hal ini senada dengan pendapat Posner[7] yang mengemukakan bahwa hukum yang diteliti akan terhalang oleh karakter hukum itu sendiri, sehingga ada pemikiran bahwa hukum itu tidak dapat dibentuk secara objektif bila berhubungan dengan dunia yang sebenarnya dengan hukum. Bagaimanapun objektivitas hukum harus dibingkai dalam budaya yang tidak satu. Hakekat otonomi daerah ditinjau secara yuridis adalah pemberian kebebasan oleh Pemerintah kepada Permda untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah. Pemberian kebebasan mengambil kebijakan daerah ini sangat terbatas, karena harus dalam koridor kebijakan Pemerintah. Dalam mengembangkan keanekaragaman daerah, daerah diberikan kebebasan menyusun produk hukum daerah berdasarkan ciri khas dan karakteristik daerah. Pemberian otonomi daerah dalam negara kesatuan, sudah tentu harus berpedoman pada garis kebijakan Pemerintah. Ciri khas dan karakteristik daerah dapat dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah.
Pembuat undang-undang dan juga Perda merupakan perwakilan dari warga negara yang tidak hanya membuat hukum untuk orang-orang tapi juga menjamin hukum dalam pentingya perasaan bagi orang-orang. Perananlegislator bukan hanya berunding mengenai pembuatan undang-undang atau Perda dari perspektif tindakan baik seseorang secara objektif. Pekerjaan legislator, sebaliknya, adalah membuat undang-undang dan Perda dari perspektif orang-orang, mengambil pendapat mereka, perilaku, pilihan mereka dan seterusnya, sehingga undang-undang dan Perda mengalir yang dihasilkan dapat merefleksikan pandangan orang-orang tersebut mengenai apa yang wajib dilakukan. Di sini muncul partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan (daerah) dapat diartikan sebagai partisipasi politik dan partisipasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.[8]
Dengan demikian, aspek kepentingan umum, yang mesti menjadi perhatian utama dalam pembentukan Perda (materi muatannya) adalah kepentingan umum masyarakat di daerah. Sehingga aspirasi masyarakat di daerah terakomodir serta dapat menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Lainnya halnya materi muatan produk peraturan perundang-undangan lainnya yang harus melihat serta nasional aspek kepentingan umumnya. Karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda wilayah keberlakuannya adalah secara nasional.
Kedudukan Perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama undang-undang yang memberikan dasar legalitas dengan memberikan kewenangan delegasi legislasi (delegated legislation). Kedudukan Perda ini merupakan produk hukum dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi pengawasan terhadap Perda telah diatur dalam undang-undang, bahwa Perda dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan tata cara pengawasan dilakukan oleh Pemerintah dimana terdapat kewajiban Pemda untuk memberikan Perda dimaksud setelah disahkan sesuai dengan prosedural tertentu. Ontologi dari setiap undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah termasuk adanya pengawasan mencerminkan politik hukum yang merupakan sikap Pemerintah yang didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Politik hukum pengawasan ini terkait dengan pengawasan terhadap Perda maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Politik hukum pengawasan ini akan menentukan sikap Pemerintah yang lebih didasarkan pada pendekatan pemerintahan yang kuat (strong government), keamanan nasional (nationality stability), maupun pemerintahan yang demokratis yang merupakan landasan politik perundang-undangan.
Menurut Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Sukardi[9], tipe negara demokrasi dilandasi atas asas kebebasan dan persamaan. Asas ini menjamin kepastian keinginan warga untuk melakukan kegiatan secara bersama menurut yang dikehendaki. Sedangkan Meuwissen menyatakan bahwa: “de democratie is de staatsvorm bij uitstek, waarin ieders vrijheid kan worden verwerkelijkt – in de grondrechten krijgt de eis tot wederzijdse tolerantie een iedereen bindende vorm – uit dien hoofde hangen grondrechten en democratie immanent samen” (terjemahan bebas: demokrasi adalah bentuk negara, dimana terutama setiap persamaan dapat diwujudkan – dalam hak-hak dasar setiap orang dapat menerima dua hal, yaitu toleransi dan perhatian secara sama – karenanya ada persamaan batiniah antara hak-hak dasar dan demokrasi.
C. Indikator Bertentangan Dengan Kepentingan Umum sebagai Dasar Pembatalan Perda
Secara konstitusional, dasar pelaksanaan supervisi dan pengawasan terhadap Perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Nomenklatur berhak menetapkan memiliki makna konstitusional bahwa pemerintahan daerah tidak secara murni membentuk Perda berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai urusan pemerintahan yang merupakan kewenangannya, tetapi penetapan atau berhak menetapkan ini merupakan hak pemerintahan daerah terhadap urusan pemerintahan yang telah ditentukan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
Dasar konstitusionalitas supervisi dan pengawasan terhadap pembentukan Perda ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 145 dan Pasal 218 UU Pemda. Pasal 145 dan Pasal 218 UU Pemda menyebutkan bahwa:
Pasal 145
(1) Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
(3) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah rnencabut Peraturan Daerah dimaksud.
(5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.
Pasal 218 :
(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;
b. Pengawasan terhadap Perda dan peraturan kepala daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 218 UU Pemda, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pengawasan terhadap Perda provinsi maupun kabupaten/kota. Pengawasan terhadap Perda dilakukan berdasarkan materi muatan Perda itu sendiri. Materi muatan Perda berdasarkan Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda adalah dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, materi muatan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, yang hanya diatur dalam pasal 136 ayat (3) UU Pemda. Ketentuan mengenai materi muatan Perda ini pun sesuai dengan Pasal 12 UU Pemda menyebutkan bahwa:
“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Dalam peraturan perundang-undangan, Perda memiliki posisi yang unik karena meski kedudukan Perda berada di bawah undang-undang, tetapi tidak terdapat kesatuan pendapat antara para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya.Perdebatan mengenai berlakunya excecutive review dan judicial review terhadap Perda menjadi pertanyaan tersendiri dalam pelaksanaan desentralisasi ini mengingat Perda adalah produk kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom.
Terkait dengan pembatalan Perda berdasarkan Pasal 145 UU Pemda, ratio legis rumusan pasal-pasal dimaksud menyatakan bahwa pembatalan Perda dikategorikan sebagai dapat dibatalkan berkaitan dengan kewenangan pembatalan. Dalam hukum administrasi dikenal adanya 3 (tiga) bentuk pembatalan, di antaranya batal karena hukum (nietigheid van rechtswege), batal (nietig), dan dapat dibatalkan (vernietigbaar). Keputusan yang tidak sah dapat berakibat nietigheid van rechtswege (batal karena hukum), nietig (batal), atau vernietigbaar (dapat dibatalkan). Nietig berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Vernietigbaar berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibat hukumnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintahan lain yang kompeten. Nietigheid van rechtswege artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan itu. Tindakan pemerintahan dapat berakibat batal karena hukum, batal atau dapat dibatalkan tergantung pada essential-tidaknya kekurangan yang terdapat di dalam keputusan itu.
Pembatalan Perda berdasarkan Pasal 145 UU Pemda dikategorikan sebagai dapat dibatalkan (vernietigbaar) dan batal demi hukum (nietigheid van rechtwege). Tentunya pembatalan ini tidak terkait dengan cacat wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, tetapi pembatalan ini seyogyanya lebih menitikberatkan pada cacat materi. Dalam hal ini dikatakan cacat materi karena materi Perda yang dibatalkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.
Indikator pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum masih merupakan sesuatu yang debatable. Makna Perda sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi indikator pembatalan Perda harus diperjelas, karena pembentukan Perda merupakan amanat UU Pemda. Hal ini berkaitan dengan Perda tentang perizinan merupakan amanat UU Pemda yang merupakan wewenang daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Akibat adanya ketentuan yang membuat norma yang tidak jelas, memberikan kemungkinan bagi Pemerintah untuk melakukan arena pilihan yang terbuka lebar untuk menentukan apakah Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud memiliki substansi pengaturan yang tidak sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945 dan UU Pemda. Oleh karena itu, harus ditentukan batasan pembatalan Perda dengan menggunakan indikator peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Indikator kepentingan umum dalam pembatalan Perda pun merupakan norma kabur yang membuka ruang bagi Pemerintah untuk melakukan penafsiran terhadap norma kepentingan umum. Ketentuan mengenai “kepentingan umum” dapat ditemui dalam penjelasan pasal 136 ayat (4) UU Pemda menyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggungnya ketenteraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif” dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah, yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan umum meliputi kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu Daerah seperti norma agama, adat istiadat, budaya serta susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Pengggunaan kata kepentingan umum telah lazim digunakan di dalam perundang-undangan maupun di dalam praktek. Mengutip pendapat Couch and Shughart, 1998, Michael Hantke Domas[10] menyatakan:
“in the law (as seen) public interest has helped judge to solve controversies on regulation; whereas in politics it has been a goal to achieve by regulation. In the latter application, publik interest has been a vague aim, because it has not had a clear definition of its content. This has been a controversial area where academics have advanced different interpretations of the exact use the concept of public interest in politic”.
Kepentingan umum dalam teori penormaan dikategorikan sebagai konsep kabur (blanket norm), yang menurut J. J. H. Bruggink[11], pengertian yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat didefinisikan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas. Untuk memahami norma kabur diperlukan penafsiran. Adanya indikator kepentingan umum sebagai norma kabur telah membuka ruang bagi Pemerintah untuk menafsir kepentingan umum, walaupun telah diartikan pengertian kepentingan umum tetapi masih belum memberikan rinciannya secara persis. Terkait dengan indikator larangan dimaksud, maka seyogyanya Pemerintah merinci apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, karena terkait dengan asas kepastian hukum “tidak dilarang berarti boleh”, maka pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membentuk Perda dan adanya kejelasan bagi Pemerintah dalam membatalkan Perda.
Kepentingan umum memiliki esensi yang sangat penting dalam pembentukan Perda, karena tujuan pembentukan Perda adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat di daerah. Berbagai aktivitas masyarakat dilakukan dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perda. Perda tidak hanya mengatur kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, namun juga mengatur kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitasnya, masyarakat menjadi subyek yang turut mendukung kehidupan sosial dan ekonomi di daerah. Dengan alasan ini sudah seyogyanya pembentuk Perda harus memperhatikan dengan sungguh aspek kepentingan umum yang dimuat di dalam Perda sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat ketika Perda tersebut akan dilaksanakan.
D. Penutup
Perda di satu sisi harus memperhatikan dan mengakomodir kepentingan pembangunan di daerahnya, tetapi di sisi lain kepentingan nasional juga harus diperhatikan dan diakomodir dalam materi muatan sebuah Perda. Kepentingan umum sangat kompleks, kepentingan umum tidak selalu harus dipahami sebagai kepentingan nasional, kepentingan daerah dapat juga merupakan kepentingan umum karena meliputi semua kepentingan di daerah secara komunal. Kepentingan daerah berarti menyangkut kepentingan semua individu di daerah secara keseluruhan. Sementara kepentingan pada masing-masing daerah berbeda-beda salah satunya berdasarkan ciri khas atau karakteristik daerahnya. Dengan kemajemukan yang ada, maka indikator bertentangan dengan kepentingan umum sebagai alasan pembatalan Perda, bahwa kepentingan umum pada masing-masing daerah sangat kompleks, belum lagi ditambah dengan kepentingan nasional yang kadang tidak sejalan dengan kepentingan daerah. Indikator bertentangan dengan kepentingan umum (masyarakat) tidak merincikan kepentingan umum yang dimaksud itu adalah kepentingan masyarakat di daerah atau kepentingan nasional. Kepentingan masyarakat di daerah merupakan kepentingan umum dengan alasan bahwa kepentingan daerah bukan saja menjadi milik pribadi atau individu masyarakat di daerah, tetapi kepentingan daerah merupakan kepentingan bersama (komunal) masyarakat di daerah. Kepentingan di daerah mestinya lebih menjadi perhatian utama dalam pembentukan suatu Perda, khususnya dalam perumusan materi muatan Perda karena ruang lingkup keberlakuan suatu Perda, hanya pada daerah itu sendiri, bukan berlaku secara nasional, tetapi nilai-nilai kesatuan sebagai wujud suatu negara kesatuan harus tetap diperhatikan sehingga tidak mengakibatkan perpecahan antar daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Bruggink, J.J.H.. 1999.Rechtsreflecties, terjemahan Arief Sidartha, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Burkens, M.C., 1997, Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, W.E.J. Tjeenk Willenk, Deventer.
Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli (editors). 1983. Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi.
Domas, Michael Hantke. 2003. “The Public Interest Theory of Regulation: Non-Existence or Misinterpretation”, European Journal of Law and Economics, Kluwer Academic Publisher, Manufactured in The Netherlands,
Hadjon,Philipus M. 1997. “Pengkajian Ilmu Hukum”. Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
Hattu, Hengky. 2010. Model Undang-Undang Berkarakter Responsif Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
Huntington, Samuel P., dan Joan Nelson, 1994, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.
Hutchinson,Terry. 2002. Researching and Writing in Law. Lawbook Co.
Posner, Richard A., 1990. The Problems of Jurisprudence. Harvard University.
Seerden, Rene and Frits Stroink (eds). 2002. Administrative Law of the European Union, Its Member States and The United States (A Comparative Analysis), Intersentia Uitgevers Antwerpen, Groningen.
Sukardi, “Pengawasan Perda (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Timur)” dalam Jurnal Konstitusi, (Surabaya: Puskoling-FH Universitas Airlangga, Vol. II, No. 1, Juni 2009).
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.
[1] Pernah dimuat dalam Jurnal Ilmiah SASI. Volume 18, Nomor 1, Januari-Maret 2012.
[2] Staf Pengajar pada Bagian HTN/HAN FH Unpatti.
[3]Sukardi, Pengawasan Peraturan Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Timur) dalam Jurnal Konstitusi, (Surabaya: Puskoling-FH Universitas Airlangga, Vol. II, No. 1, Juni 2009), hlm. 142.
[4]Dennis A. Rondinelli and G. Shabbier Cheema, “Implementing Decentralization Policies: An Introduction” dalam G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (editors), Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi, 1983, h. 18.
[5]Burkens, M.C., 1997, Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, W.E.J. Tjeenk Willenk, Deventer, p.260-263
[6]A. W. Bradley and K. D. Ewing. Constitutional and Administrative Law. 13th edition. Hlm. 650-651
[7]Richard A. Posner. 1990. The Problems of Jurisprudence. Harvard University.
[8] Huntington, Samuel P., dan Joan Nelson, 1994, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.
[9]Sukardi. Op.cit. hlm. 256.
[10]Michael Hantke Domas, “The Public Interest Theory of Regulation: Non-Existence or Misinterpretation”, European Journal of Law and Economics, Kluwer Academic Publisher, Manufactured in The Netherlands, 2003, hlm. 173
[11] Bruggink, J.J.H.. 1999.Rechtsreflecties, terjemahan Arief Sidartha, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta. p. 61.